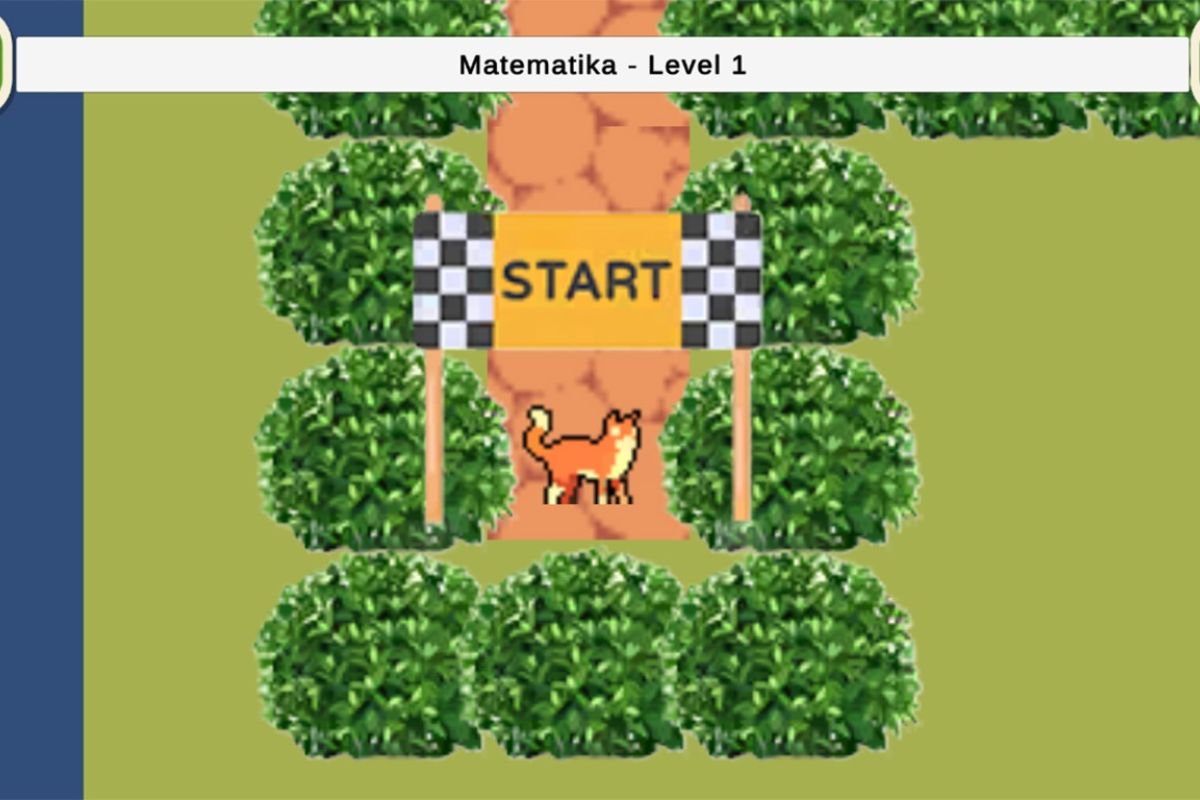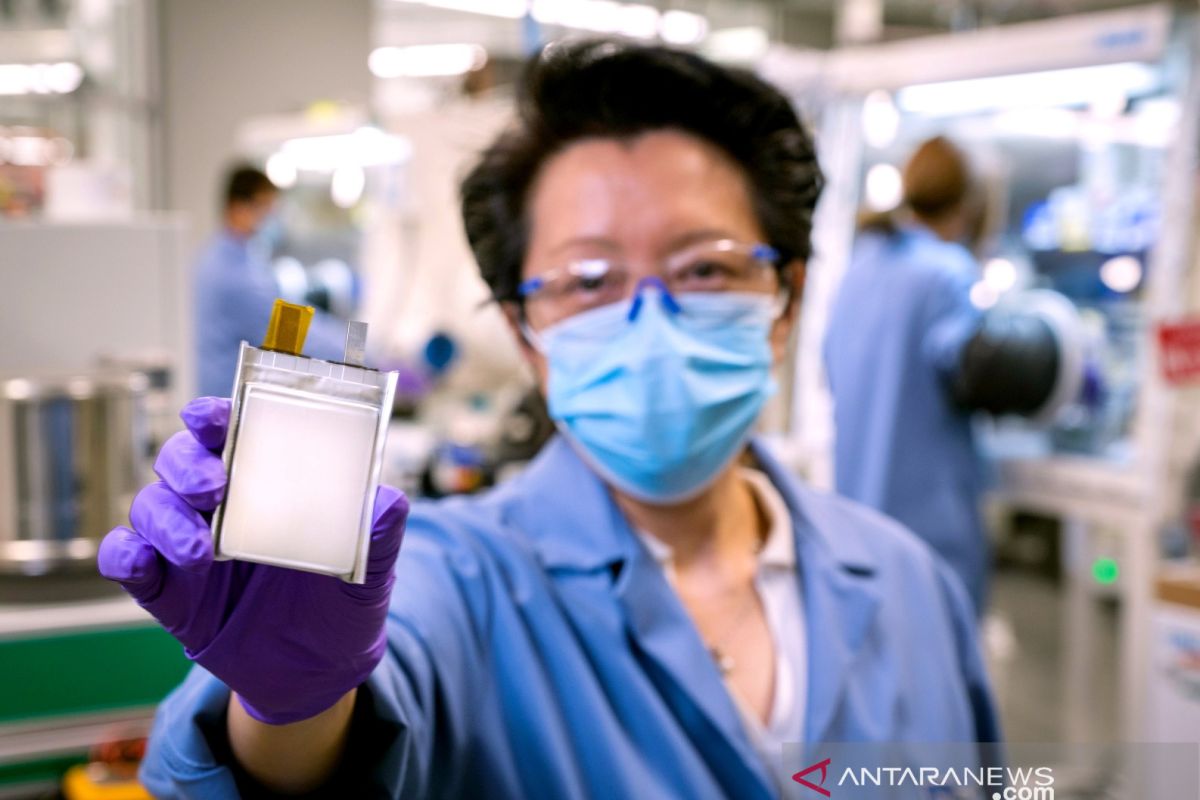Geopolitik global kontemporer ditandai oleh kembalinya politik kekuatan dalam bentuk konflik terbuka dan rivalitas strategis jangka panjang.
Perang Rusia–Ukraina, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan ketegangan berulang di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa tatanan internasional bergerak menjauh dari multilateralisme menuju kompetisi berbasis kekuasaan.
Dalam situasi ini, negara-negara sering diukur bukan hanya dari kapasitas militernya, melainkan juga dari kejelasan orientasi, konsistensi nilai, dan kepercayaan diri dalam menentukan posisi.
Bagi Indonesia, persoalan mendasarnya bukan terletak pada absennya sumber daya, melainkan pada sejauh mana bangsa ini mampu membaca dirinya sendiri dalam lintasan sejarah dan menjadikannya dasar kebijakan geopolitik yang rasional.
Dalam perspektif historis, anggapan bahwa Indonesia adalah aktor pinggiran dalam geopolitik global tidak memiliki landasan empiris yang kuat. Sejak awal Masehi, wilayah Nusantara telah berfungsi sebagai pusat peradaban maritim dunia.
Jalur pelayaran yang melintasi Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Natuna bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan juga arena perjumpaan peradaban India, Arab, Cina, dan kemudian Eropa.
Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 merupakan kekuatan maritim yang mengendalikan arus perdagangan dan pengetahuan, sementara Majapahit pada abad ke-14 membangun tatanan politik berbasis integrasi kawasan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Nusantara bukan wilayah pasif, melainkan produsen nilai, norma, dan tata kelola dalam sistem regional.
Gagasan ini dipertegas oleh Yudi Latif ketika memaknai Pancasila bukan sekadar dokumen normatif negara modern, melainkan juga sebagai kristalisasi pengalaman panjang peradaban Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial lahir dari praktik historis masyarakat Nusantara dalam mengelola pluralitas dan relasi kekuasaan.
Dengan kata lain, kepercayaan diri bangsa Indonesia memiliki fondasi historis dan kultural yang objektif. Ia bukan hasil konstruksi ideologis pascakemerdekaan, melainkan kesinambungan dari peradaban yang telah teruji oleh waktu.
Dalam konteks negara modern, kesinambungan peradaban tersebut tecermin dalam peran Indonesia pada Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah, melainkan juga sebagai penggagas forum global yang menantang dominasi bipolar Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Bandung menjadi simbol bahwa negara-negara bekas koloni dapat berbicara atas nama dirinya sendiri. Prinsip hidup berdampingan secara damai dan penolakan terhadap politik blok kemudian menjadi fondasi Gerakan Non-Blok.
Peristiwa ini merupakan bukti historis bahwa Indonesia mampu memimpin secara normatif, bukan melalui kekuatan koersif, melainkan melalui legitimasi moral dan pengalaman sejarah.
Oleh karena itu, kepercayaan diri bangsa dalam geopolitik harus dipahami sebagai kapasitas normatif dan institusional untuk bertindak konsisten dengan jati diri tersebut. Dalam perspektif negara hukum, kepercayaan diri terwujud ketika kebijakan strategis bukan sekadar sah secara formal, melainkan juga tepat secara substantif.
Ratifikasi UNCLOS 1982 dan pengakuan konsep negara kepulauan merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia tidak hanya mengikuti hukum internasional, tetapi juga ikut membentuknya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan struktural untuk memengaruhi tatanan global ketika bertindak berbasis kepentingan nasional yang dirumuskan secara matang.
Masalah muncul ketika memori historis dan kesadaran peradaban ini terputus dari praktik kebijakan kontemporer. Geopolitik sering direduksi menjadi urusan elite diplomasi dan pertahanan, sementara dimensi sosial dan kewargaan terpinggirkan. Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa daya tahan bangsa justru terletak pada keterlibatan masyarakat.
Dari jaringan perdagangan Nusantara, perlawanan terhadap kolonialisme, hingga konsolidasi negara pasca-kemerdekaan, partisipasi publik selalu menjadi elemen kunci. Ketika masyarakat bukan lagi diposisikan sebagai subjek geopolitik, kepercayaan diri bangsa kehilangan basis sosialnya.
Evaluasi kritis terhadap situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi substantif. Secara formal, Indonesia konsisten menyatakan politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian.
Namun secara substantif, tanpa penguatan kesadaran geopolitik publik, posisi tersebut mudah ditafsirkan sebagai sikap pasif. Dampak konflik global justru paling nyata dirasakan di wilayah perbatasan dan kawasan maritim, dalam bentuk tekanan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan kompetisi pengaruh asing. Tanpa basis kewargaan yang kuat, kebijakan negara berisiko kehilangan dukungan dan efektivitas jangka panjang.
Dalam kerangka ini, keberadaan organisasi masyarakat sipil yang berakar pada nilai kebangsaan memiliki relevansi strategis. Jejaring alumni bela negara—termasuk Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI)—dapat dipahami sebagai bagian dari modal sosial yang menghubungkan negara dengan masyarakat.
Peran semacam ini bukan dalam arti militeristik, melainkan sebagai medium pendidikan kewargaan, penguatan disiplin sosial, ...

 1 hour ago
2
1 hour ago
2