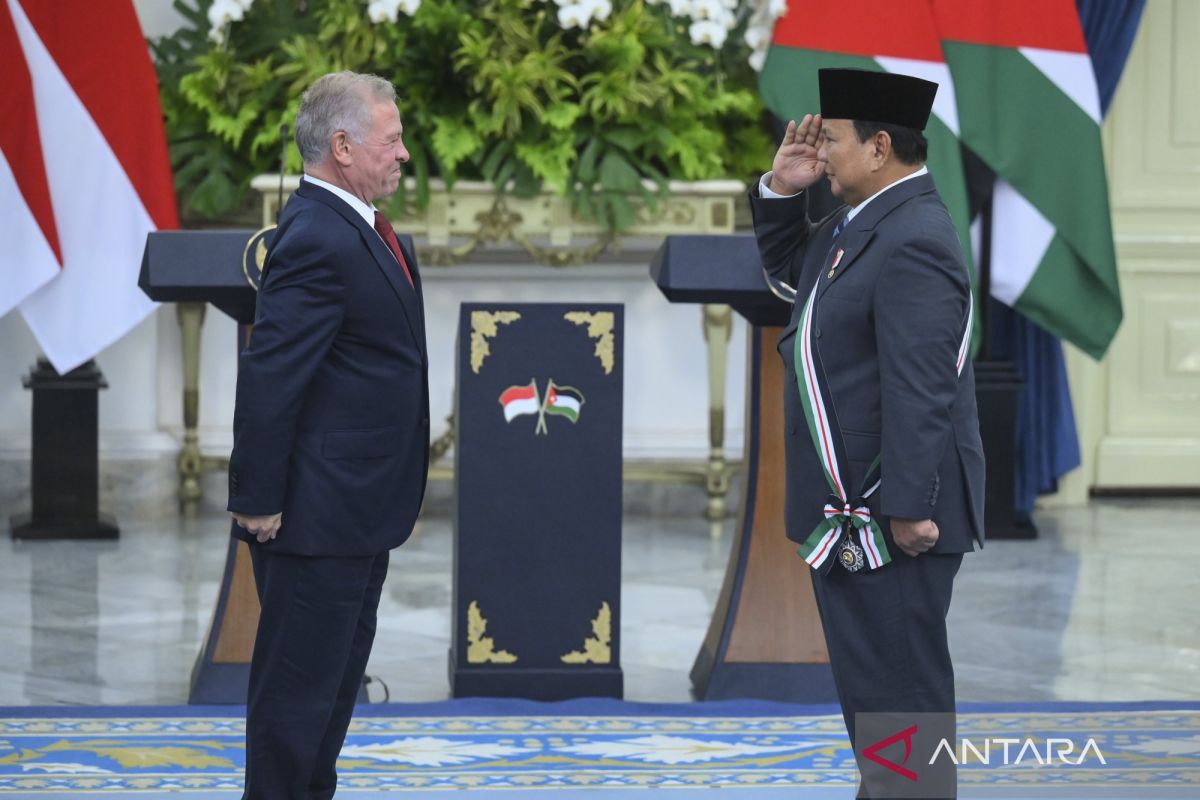Di dunia pendidikan, istilah "Group Contingency" (Sistem Hadiah Kelompok) sering dipuji sebagai obat mujarab untuk mengatasi kekacauan di kelas. Strategi ini berakar kuat pada teori pengkondisian operan (operant conditioning) dari B.F. Skinner, yang menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung akan diulang.
Konsepnya sederhana: sebuah sistem terstruktur di mana hadiah, baik itu dalam wujud konkret (seperti, stiker, permen, cokelat) maupun dalam wujud abstrak (waktu istirahat tambahan ataupun "tiket pulang"), diberikan berdasarkan perilaku kelompok. Namun, ketika strategi yang berpusat pada teori Barat ini diterjemahkan ke dalam kelas-kelas di Indonesia yang seringkali padat dan kekurangan dana, teori tersebut berbenturan keras dengan tembok realitas sosial-ekonomi.
Sebagai guru bahasa Inggris yang terbiasa mengisi jam-jam pelajaran menjelang jam istirahat dan pulang sekolah, saya telah menerapkan metode ini. Menjelang jam istirahat, saya menerapkan Kontingensi Independen (Independent Contigency): siswa/i yang catatan dan tugasnya lengkap boleh keluar; mereka yang tidak, harus tinggal di kelas. Menjelang bel pulang, saya beralih ke pendekatan Kontingensi Interdependen (Interdependent Contigency): jika ada satu saja siswa yang masih ribut, seluruh kelas tidak boleh pulang. Hasilnya instan. Tekanan dari teman sebaya langsung terasa, dan kelas pun menjadi hening dan disiplin.
Namun, muncul tren yang mengkhawatirkan. Dalam berbagai video Berbagi Praktik Baik dan testimoni guru di media sosial seperti TikTok dan Instagram, yang sering kali merujuk pada metode gamifikasi di kelas, beberapa pendidik memperlihatkan pemberian hadiah konkret seperti permen, stiker, hingga cokelat sebagai alat kontrol kelas.
Secara global, tren ini terdokumentasi dengan jelas. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Positive Behavior Interventions mengungkapkan bahwa mayoritas sistem dukungan perilaku positif (PBIS) di sekolah-sekolah sangat bergantung pada tangible reinforcers. Di Amerika Serikat, laporan dari Education Week Research Center menemukan bahwa sekitar 80% guru menggunakan hadiah konkret sebagai bagian dari strategi manajemen kelas mereka.
Saya memandang tren pemberian hadiah konkret ini sebagai langkah mundur. Memberikan benda fisik demi ketertiban bukan hanya membebani finansial guru, tetapi juga mengerdilkan esensi belajar menjadi sekadar transaksi material. Saya lebih memilih pendekatan yang lebih abstrak namun bermakna, seperti “tiket keluar” atau "tiket pulang" (apresiasi simbolis). Hadiah abstrak ini jauh lebih efektif dalam menjaga martabat guru dan integritas kognitif siswa.
Ada dua alasan mengapa kita harus berhati-hati dengan tren hadiah konkret ini beserta dengan teori itu sendiri.
Pertama, kita harus jujur mengenai realitas guru di Indonesia, terutama para guru honorer. Pedagogi modern menuntut guru untuk menjadi mesin kepositifan, yang terus-menerus memberikan pujian dan hadiah bagi perilaku baik. Namun, bagaimana mungkin seorang guru yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena upah yang minim, diharapkan untuk terus-menerus merancang kebahagiaan bagi siswa-siswinya? Kita meminta guru menjadi arsitek psikologis di saat mereka sendiri berada dalam fase bertahan hidup secara ekonomi. Seorang guru yang tidak mampu membiayai "kebahagiaannya sendiri" di akhir bulan akan merasa batinnya terkuras jika harus terus-menerus menyediakannya bagi orang lain.
Kedua, ada risiko psikologis yang disebut overjustification effect. Penelitian dari psikolog Edward Deci dan Richard Ryan menunjukkan bahwa pemberian hadiah konkret yang berlebihan dapat mematikan minat intrinsik. Jika kita terus-menerus menyuap siswa dengan hadiah fisik, kita melatih mereka untuk bertanya, "Apa untungnya buat saya?" alih-alih memahami mengapa ilmu tersebut vital bagi mereka. Ini tentu berbahaya. Kita butuh siswa yang disiplin dan berilmu agar mereka tidak mudah "dibodoh-bodohi" di masa depan, bukan siswa yang hanya bergerak jika ada cokelat di depan mata.
Oleh karena itu, manajemen kelas harus bergeser dari model transaksional ke model transformasional. Tugas utama guru adalah menjembatani jarak antara pelajaran yang membosankan dengan peluang bertahan hidup siswa. Selesaikan tugas bukan demi stiker, melainkan demi mempersenjatai diri dengan "baju besi" mental untuk mencari kerja atau meraih beasiswa.
Sistem hadiah kelompok tidak boleh menjadi seperti ajang suap. Ia harus menjadi simulasi tanggung-jawab sosial. Ketika kelas ditahan karena satu siswa gaduh, kita sedang mengajarkan bahwa di masyarakat, tindakan satu orang berdampak pada banyak orang. Pada akhirnya, hadiah terbaik yang bisa diberikan guru bukanlah sesuatu yang habis dimakan, melainkan kemampuan siswa untuk menjalani hidup dengan martabat dan pikiran yang tidak mudah dimanipulasi.***

 1 day ago
11
1 day ago
11