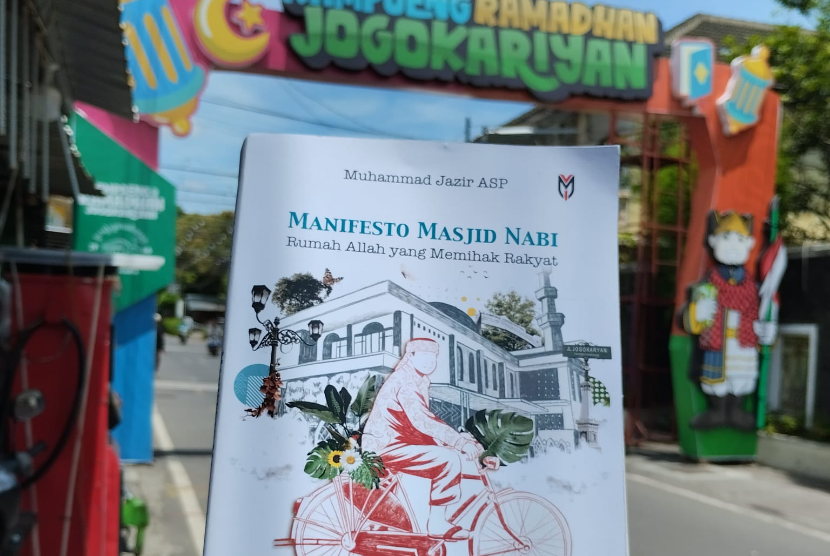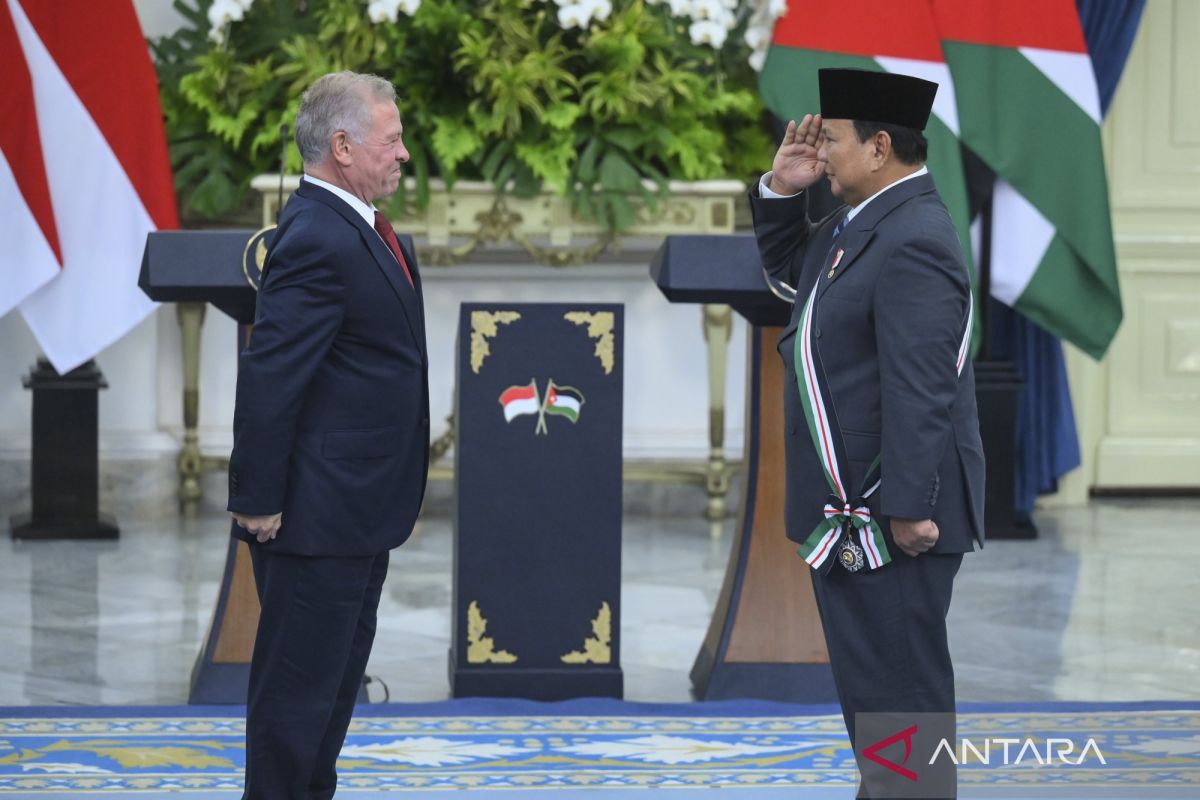Tulisan ini bukan sekadar kritik, melainkan potret diagnostik berdasarkan data, teori, dan pengamatan langsung di lapangan— khususnya dalam dinamika pemerintahan daerah yang sering menjadi cermin miniatur Indonesia.
Secara teori, demokrasi bukan hanya tentang pemilu, melainkan juga accountability, partisipasi, dan kebebasan berekspresi.
Namun, menurut The Economist Intelligence Unit (2024), Indeks Demokrasi Indonesia turun ke peringkat 65 dunia dengan skor 6,48. Penurunan ini bukan kebetulan.
Di tingkat akar rumput, partisipasi politik warga makin menipis. Data KPU (2024) mencatat partisipasi pemilu hanya 81,78%, terendah dalam dua dekade terakhir. Ini gejala democratic fatigue: rakyat lelah dengan politik transaksional, kampanye hitam, dan janji yang menguap pasca-pemilu.
Teori delegative democracy (O’Donnell, 1994) relevan di sini: pemimpin terpilih memerintah dengan mandat luas, tetapi mekanisme check and balance lemah. Akibatnya, kebijakan sering reaktif, tidak partisipatif, dan lebih mengutamakan kepentingan elite politik daripada publik.
Di daerah, situasi lebih memprihatinkan. Pilkada kerap dibayangi politik uang dan dinasti. Ruang dialog seperti musrenbang sering menjadi formalitas belaka. Hasilnya, kebijakan daerah kerap tak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ekonomi yang Tumbuh tapi Pincang
Data BPS September 2024 menunjukkan Gini Ratio tetap tinggi di 0,384. Artinya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin nyaris tak beranjak. Yang lebih mengkhawatirkan: 20% kelompok terbawah hanya menikmati 6,5% dari total pengeluaran nasional, sementara 20% teratas menguasai hampir separuhnya.
Kita juga terjebak dalam middle-income trap: pertumbuhan ditopang konsumsi dan ekspor komoditas, bukan inovasi atau industri bernilai tambah tinggi. Investasi asing langsung (FDI) memang
masuk, tetapi sering ke sektor ekstraktif yang minim penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Di tingkat daerah, ketergantungan pada transfer pusat (DAU dan DAK) mencapai 70% dari APBD di banyak kabupaten. Otonomi daerah malah jadi kutukan ketika kapasitas fiskal dan SDM terbatas. UMKM—yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal—kesulitan akses pembiayaan dan pasar.
Pemerintahan yang Terfragmentasi
Contoh nyata: program pengentasan stunting. Meski dana digelontorkan, prevalensi stunting di sejumlah daerah justru stagnan karena salah sasaran dan tumpang tindih program. Ini cermin policy incoherence yang mahal harganya: anggaran membengkak, hasil minim.
Birokrasi kita juga masih terjebak dalam silo mentality. Setiap kementerian dan dinas daerah bekerja sendiri-sendiri, tanpa sinergi. Pelayanan publik masih lambat dan berbelit, meski jargon "digitalisasi" terus digaungkan. E-budgeting, misalnya, baru diterapkan di 45% daerah. Sisanya masih manual—dan rentan korupsi.

 4 hours ago
1
4 hours ago
1