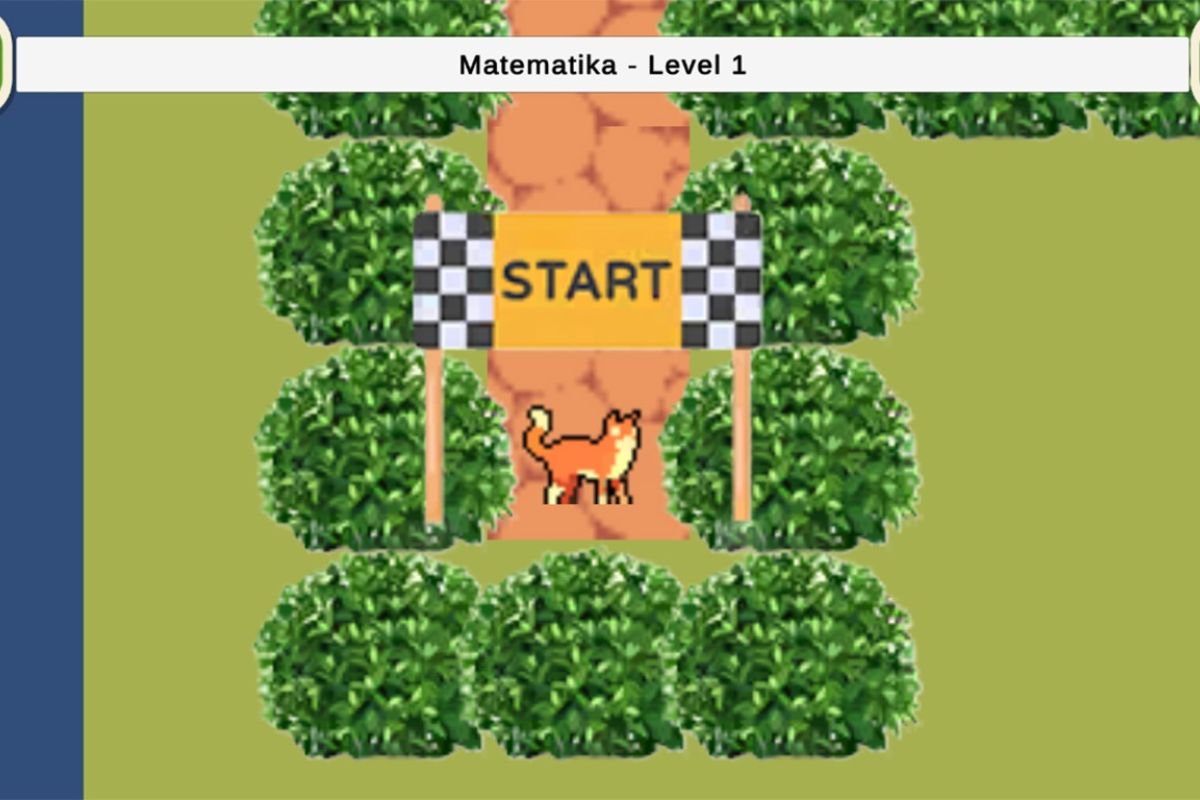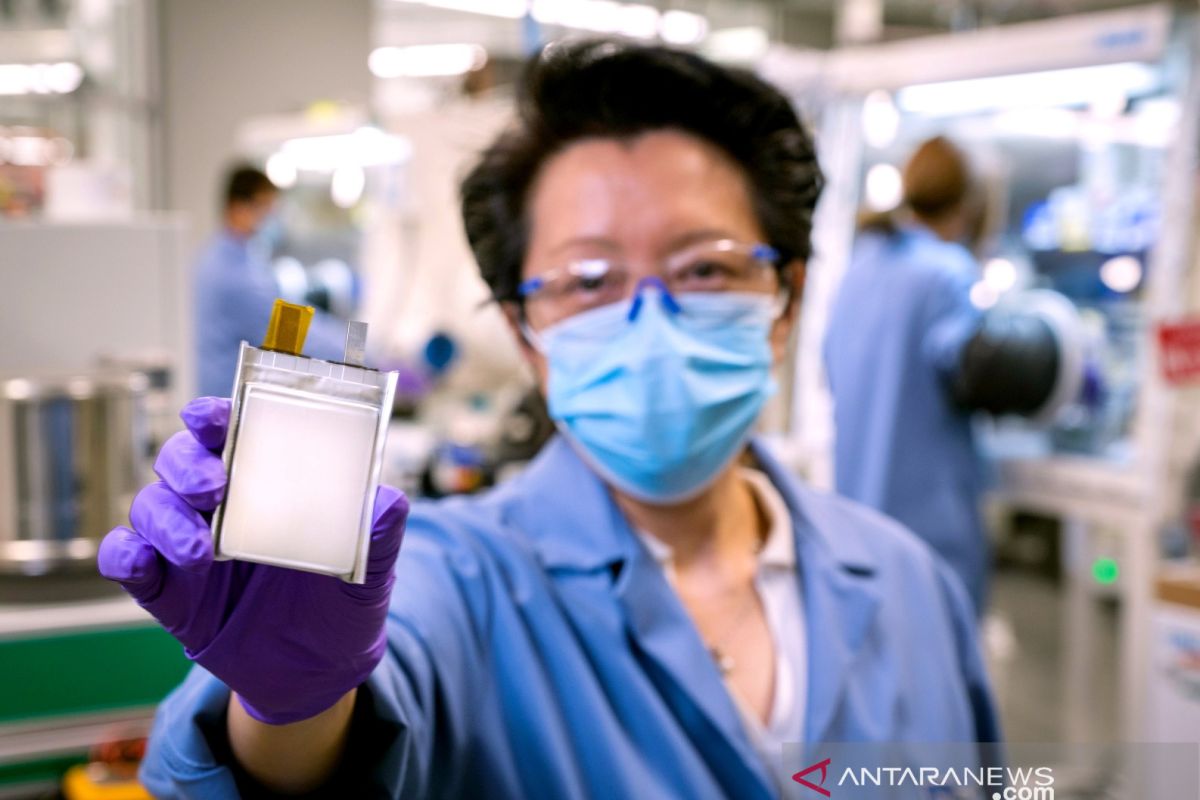Jakarta (ANTARA) - Restitusi pajak merupakan konsekuensi logis dari sistem self-assessment yang dianut Indonesia. Ketika wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya terutang, negara berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut.
Namun dalam praktiknya, restitusi bukan sekadar isu administratif, melainkan titik temu antara kepastian hukum, keberlanjutan fiskal, dan risiko fraud.
Di satu sisi, restitusi yang lambat menurunkan kepercayaan wajib pajak dan mengganggu arus kas dunia usaha. Sebaliknya, restitusi yang terlalu longgar berpotensi menggerus penerimaan negara dan membuka ruang moral hazard serta negosiasi yang tidak sehat.
Dalam tiga tahun terakhir, restitusi pajak, khususnya dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi dinamika penerimaan negara.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan nilai restitusi pajak pada 2022 mencapai sekitar Rp265 triliun, meningkat menjadi sekitar Rp300 triliun pada 2023, dan tetap berada pada level tinggi sepanjang 2024 seiring normalisasi ekonomi dan peningkatan klaim restitusi PPN oleh sektor ekspor dan industri berbasis rantai pasok global (Kemenkeu, 2024).
Pada tahun 2025, realisasi restitusi pajak di Indonesia meningkat tajam dan memberi tekanan nyata terhadap penerimaan negara. Hingga akhir Februari 2025, total restitusi yang dibayarkan mencapai sekitar Rp111,04 triliun, angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp57,5 triliun), didominasi oleh restitusi PPN dan PPh badan.
Selanjutnya, hingga Oktober 2025, realisasi restitusi semakin melonjak menjadi sekitar Rp340,52 triliun meningkat sekitar 36,4 persen dibandingkan Oktober 2024 yang mendorong kontraksi penerimaan pajak neto nasional meskipun penerimaan bruto secara nominal meningkat.
Akibatnya, neto penerimaan pajak turun sekitar 3,9 persen year-on-year hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa volume restitusi yang tinggi telah menggerus realisasi penerimaan dalam kerangka APBN 2025.
Fenomena ini semakin memunculkan diskusi tentang perlunya pengendalian restitusi, karena selain memberi tekanan fiskal, proses yang kurang berbasis risiko berpotensi membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan dalam penetapan besaran restitusi yang dibayarkan.
Dalam perspektif fiskal, restitusi yang besar dan volatil cenderung bersifat kontraproduktif terhadap target penerimaan negara jangka pendek. Meskipun secara konsep restitusi bukanlah “kehilangan” penerimaan, secara kas restitusi tetap menggerus ruang fiskal, terutama ketika negara menghadapi kebutuhan belanja yang tinggi.
Sejumlah kasus penegakan hukum baik yang ditangani oleh aparat penegak hukum maupun yang diungkap dalam laporan BPK menunjukkan bahwa restitusi pajak kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara oknum aparat dan wajib pajak.
Dalam konteks inilah, pendekatan risk-based restitution menjadi relevan. Pendekatan ini tidak menafikan hak wajib pajak, tetapi menata ulang proses restitusi agar lebih selektif, berbasis data, dan berorientasi risiko.
Risk-based restitution juga dapat berperan sebagai jembatan antara kebutuhan menjaga iklim usaha melalui restitusi yang cepat dan kepentingan negara untuk menjaga penerimaan serta integritas sistem perpajakan.
Melalui desain risk-based restitution yang pruden dan kredibel, pendekatan ini mampu mengurangi potensi penyelewengan, menekan ruang negosiasi informal, sekaligus menjaga target penerimaan negara tetap realistis dan berkelanjutan.
Tekanan fiskal
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

 7 hours ago
1
7 hours ago
1