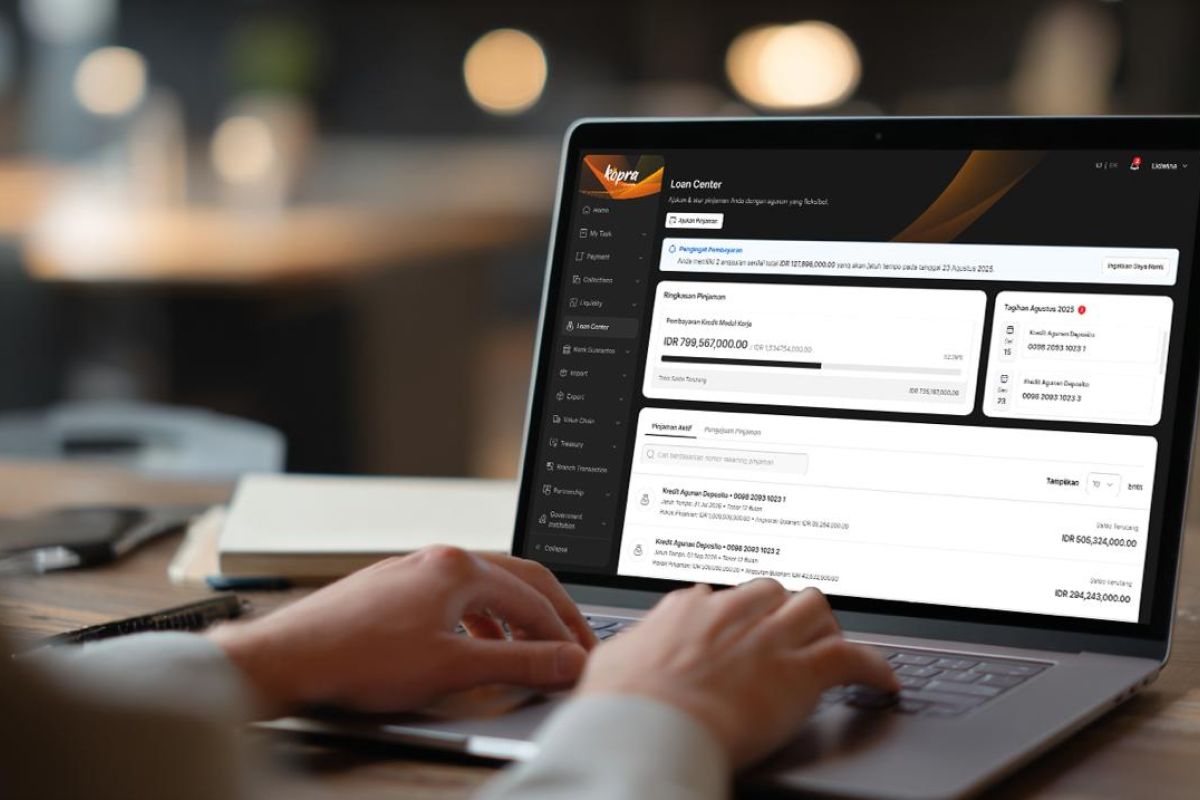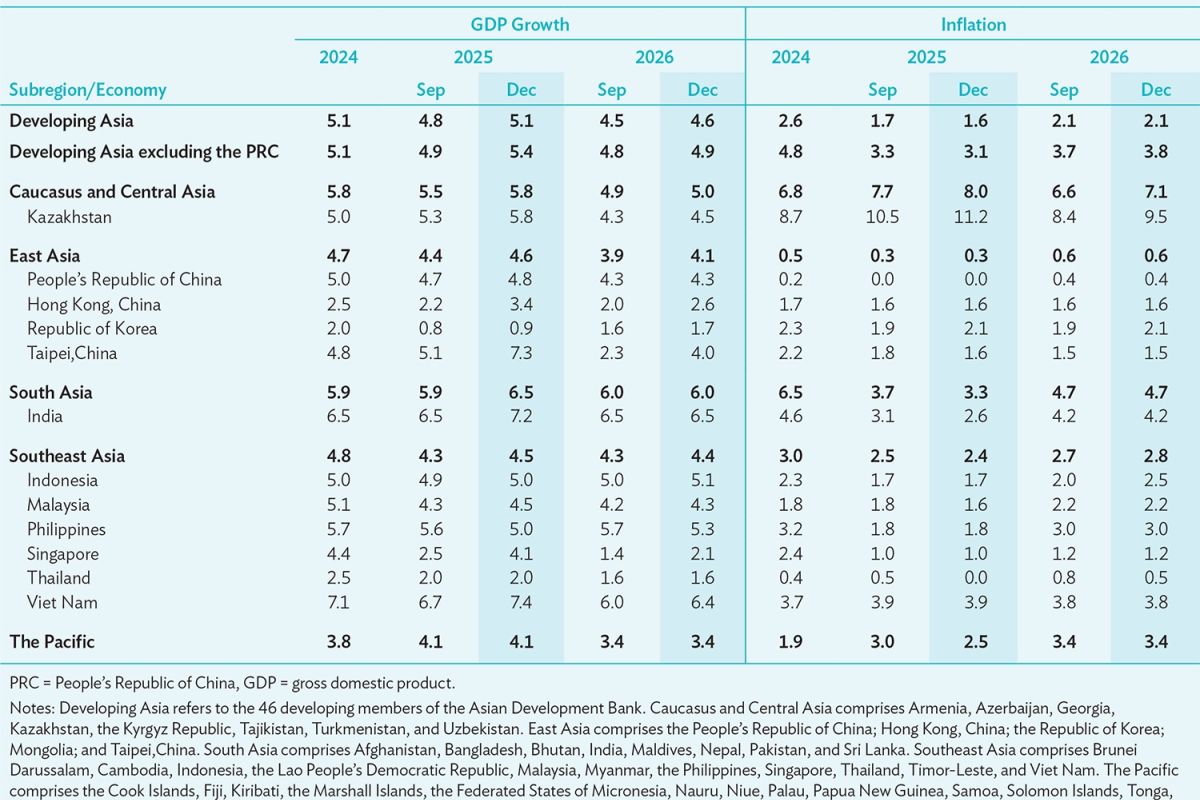Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, istilah insentif pajak begitu sering menghiasi ruang publik. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu alat utama kebijakan fiskal untuk menjaga daya saing, menarik investasi, dan menumbuhkan lapangan kerja.
Dari tax holiday, hingga super deduction, dari pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk ditanggung pemerintah. Beragam fasilitas itu diharapkan dapat memberi dorongan tambahan bagi ekonomi nasional.
Hanya saja, semakin lama, kita mulai dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah semua insentif itu masih relevan dan efektif? Apakah setiap fasilitas benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan penerimaan negara yang dikorbankan? Dan apakah kita masih bisa terus bergantung pada kebijakan fiskal berbasis insentif, ketika ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin sempit?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin penting di tengah meningkatnya beban fiskal dan tekanan pembiayaan publik. Menurut laporan Kementerian Keuangan tahun 2023, nilai belanja perpajakan atau tax expenditure Indonesia telah mencapai Rp362,5 triliun, setara 1,73 persen dari PDB. Angka itu menunjukkan potensi penerimaan yang “hilang” akibat berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha.
Belanja perpajakan sebesar itu, tentu bukan hal yang kecil. Dalam konteks postur APBN, jumlah tersebut, bahkan mendekati alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi atau kesehatan masyarakat. Lain halnya dengan belanja langsung, belanja perpajakan seringkali tidak terlihat karena tersembunyi di balik kebijakan tarif dan pengecualian pajak.
Di sinilah persoalan utamanya, tidak semua insentif pajak punya dampak ekonomi yang sepadan dengan biaya fiskalnya. Beberapa program terbukti efektif, antara lain insentif pada masa pandemi yang menahan kontraksi konsumsi dan menjaga dunia usaha tetap beroperasi.
Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang terus diperpanjang, meski efeknya terhadap penciptaan kerja, ekspor, atau investasi semakin menurun. Sebagian, bahkan sudah kehilangan relevansi karena sektor penerima sudah berkembang pesat, tanpa lagi membutuhkan dorongan fiskal.
Di tengah situasi inilah, muncul gagasan yang kian mengemuka di berbagai forum ekonomi, akademik, hingga pembahasan di parlemen, yaitu perlunya penerapan sunset clause policy sebagai sebuah mekanisme yang menetapkan batas waktu dan evaluasi bagi setiap insentif pajak agar tidak menjadi beban permanen bagi fiskal negara.
Dalam konteks reformasi kebijakan fiskal Indonesia, sunset clause policy adalah simbol dari tata kelola insentif yang lebih modern, transparan, dan berbasis hasil (result-based policy). Prinsip ini akan memaksa setiap kebijakan insentif untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya, sekaligus mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya fiskal.
Lebih jauh, penerapan sunset clause policy dapat menjadi bagian penting dari reformasi insentif fiskal Indonesia, di mana arah kebijakan tidak lagi berfokus pada “kuantitas fasilitas yang diberikan,” tetapi pada “seberapa besar kualitas nyata yang dihasilkan” terhadap investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan tax ratio nasional.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

 1 month ago
31
1 month ago
31