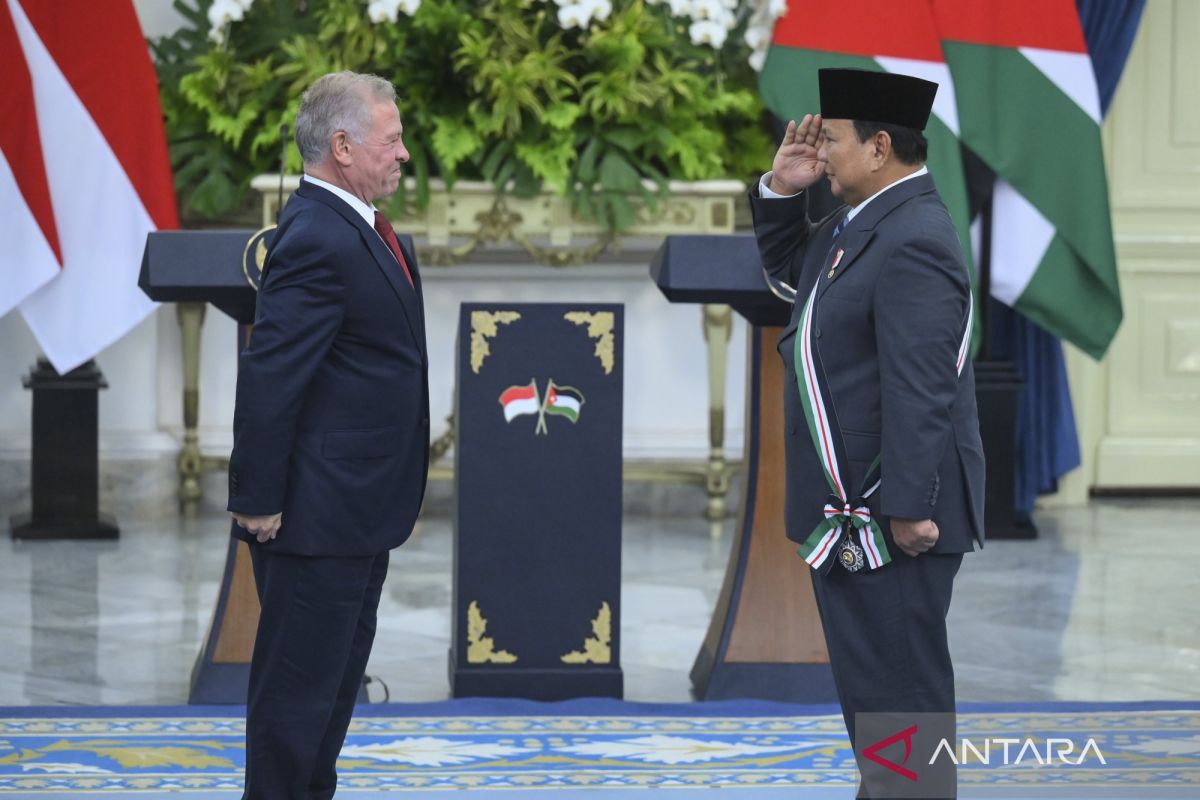Oleh : Hendarman; Analis Kebijakan Ahli Utama pada Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Ketua Dewan Pakar JFAT INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan), Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di banyak sistem pendidikan, tes kemampuan akademik diposisikan sebagai instrumen utama untuk seleksi dan diagnosis kompetensi murid. Nilai numerik, skor psikometrik, atau ranking yang dihasilkan sering kali dijadikan dasar keputusan besar—mulai dari penerimaan sekolah favorit hingga alokasi beasiswa atau jalur karier awal. Namun, sejauh mana praktik ini memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan tujuan pendidikan itu sendiri merupakan pertanyaan filosofis yang perlu dikedepankan.
Dalam filsafat ilmu, aksiologi adalah cabang yang menelaah nilai—baik itu moral, estetika, atau nilai praktis pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang tes akademik, maka kita juga harus menanyakan: nilai-nilai apa yang diukur? Nilai apa yang diabaikan? Dan nilai apa yang justru dibangun oleh proses tes itu sendiri?
Aksiologi dan Pendidikan
Aksiologi dalam filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu tidak netral tanpa nilai. Paling tidak terdapat dua rujukan klasik di bidang ini adalah. Pertama, Hilary Putnam yang dalam bukunya The Collapse of the Fact/Value Dichotomy (2002) berargumen bahwa fakta dan nilai tidak dapat dipisahkan secara tegas dalam praktik ilmu pengetahuan. Dalam konteks tes kemampuan akademik, ini menantang anggapan bahwa skor adalah “fakta murni” yang terlepas dari nilai sosial budaya.
Kedua, Nicholas Rescher, yang dalam salah satu bukunya yaitu Studies in Value Theory (2006), menunjukkan bahwa setiap penilaian ilmiah atau evaluatif pasti tersusun oleh hirarki nilai. Hirarki tersebut meliputi apa yang dianggap penting, relevan, atau layak diukur. Rescher secara implisit mengingatkan bahwa tes tidak hanya mengukur kemampuan, tetapi juga merefleksikan nilai apa yang dijunjung oleh sistem pendidikan.
Pandangan aksiologis ini menempatkan evaluasi akademik termasuk tes kemampuan akademik bukan sebagai mekanisme netral semata. Tes kemampuan akademik dianggap sebagai proses yang membawa serta nilai-nilai budaya, ekonomi, dan moral.
Bagaimana praktik tes-tes seperti ini di beberapa negara?
Praktik Beberapa Negara
Finlandia sering dikutip sebagai negara yang kurang mengandalkan tes standar sebagai penentu akhir kemampuan murid. Sistemnya lebih menitikberatkan pada penilaian formatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan karakter. Yang dapat dijadikan inferensi bahwa negara ini minim tes, tetapi memaksimalkan pembelajaran holistic. Secara aksiologis, pendekatan ini mengutamakan nilai kemanusiaan, otonomi pembelajar, dan konteks lintas disiplin—sebuah kritik implisit terhadap nilai yang semata berorientasi pada skor.
Sebagai pembanding, Singapura memiliki sistem yang terstruktur tinggi dengan tes berstandar nasional dan kompetitif. Tes pada prinsipnya adalah untuk menempatkan murid ke jalur pendidikan yang berbeda (misalnya sains/teknik vs humaniora). Pendekatan ini merefleksikan nilai-nilai seperti efisiensi, meritokrasi, dan kepastian pengukuran. Meskipun negara ini berhasil dalam kinerja penilaian PISA (Programme for International Student Assessment), kritik aksiologis menyatakan bahwa tekanan kompetitif memiliki potensi mengabaikan kesejahteraan psikologis murid.
Di Amerika, tes seperti SAT (Scholastic Aptitude Test) dan ACT (American College Testing) telah lama menjadi syarat masuk perguruan tinggi. Namun, kritik aksiologis terus berkembang terhadap penerapan kebijakan kedua tes tersebut. Kritik terutama menyangkut bahwa tes-tes tersebut cenderung menguntungkan kalangan sosial-ekonomi yang lebih berprivilege. Artinya akan memberikan kemudahan bagi mereka dengan hak istimewa atau bagi mereka yang berasal dari golongan tertentu baik secara sosial maupun ekonomi.
Aksiologi Metode Pengukuran
Di berbagai kalangan akademik maupun praktisi terdapat sejumlah isu kunci terkait aksiologi terhadap metode pengukuran. Isu pertama terkait dengan objektivitas versus nilai tersembunyi. Banyak pendukung tes standar berargumen bahwa tes memberikan data objektif tentang kemampuan. Namun, dari perspektif aksiologi, “objektivitas” ini sering kali terselubung preferensi nilai sosial. Misalnya munculnya kecenderungan mengukur kemampuan yang mudah dinilai secara kuantitatif sementara mengabaikan kreativitas atau etika kerja.
Isu kedua menyangkut nilai pendidikan yang lebih luas. Menurut John Dewey dalam bukunya Democracy and Education (1916), pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah proses sosial, Oleh karena itu pendidikan bukan hanya mempersiapkan murid untuk menghadapi tes. Aksiologi para pengikut Dewey lebih menekankan nilai pengalaman, interaksi sosial, dan pengembangan sikap kritis, bukan sekadar akumulasi skor.
Isu ketiga terkait dengan nilai keadilan dan inklusi. John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice (1999) mengusung prinsip kesetaraan kesempatan. Dalam konteks tes, hal ini mensyaratkan bahwa setiap murid memiliki akses kepada persiapan yang setara. Dalam penerapan nya kondisi ini belum selalu tercapai di banyak negara, termasuk Indonesia.
Menimbang Ulang
Dari tinjauan teori dan praktik internasional, harus dipahami bahwa tes kemampuan akademik (TKA) yang sedang diterapkan sebagai sebuah kebijakan baru, secara prinsip bukan sekadar alat teknis. Tetapi TKA seyogianya juga menjadi sebuah konstruksi nilai.
Yang perlu menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi pemegang kebijakan paling tidak terkait dengan tiga pertanyaan. Pertama, apakah tes tersebut menyeleksi atau membimbing? Kedua, apakah yang diukur relevan dengan kehidupan nyata? Yang ketiga yaitu, apakah prosesnya adil terhadap semua murid?
Dengan mengintegrasikan perspektif aksiologi maka seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan bahwa TKA adalah sebagai alat reflektif, bukan sekadar mekanisme filter.

 3 hours ago
1
3 hours ago
1