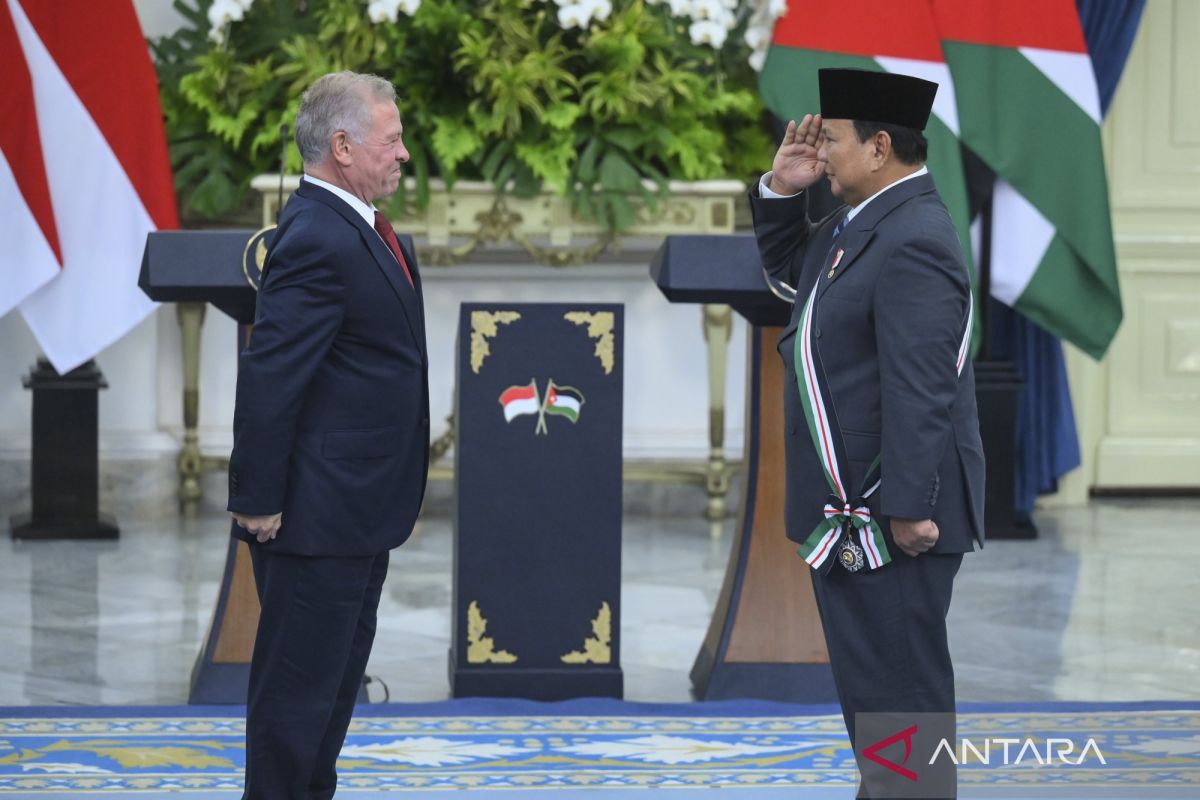Ada sebuah pemandangan yang lazim kita saksikan di hari wisuda: para dosen berbaris khidmat dengan toga kebesaran, tampak begitu megah dan berwibawa di bawah sorot lampu auditorium. Di mata para orang tua, mereka adalah penjaga gawang peradaban. Di mata mahasiswa, mereka adalah "kitab pengetahuan berjalan".
Namun, jika kita punya nyali untuk mengikuti mereka pulang setelah upacara usai, kita mungkin akan menemukan kenyataan yang sanggup merubuhkan seluruh menara gading itu dalam sekejap.
Di balik layar, profesi yang kita puja sebagai "panggilan mulia" ini sedang bertarung melawan kiamat martabat yang sangat sistemis. Pertanyaannya bukan lagi sekadar "Apakah profesi dosen masih "menarik"? melainkan "Mungkinkah kita tetap meminta otak-otak terbaik bangsa ini bertahan di kampus, sementara negara terus memperlakukan mereka layaknya relawan yang tidak butuh makan?"
Anatomi Ketimpangan: Intelektualitas yang Dimurahkan
Bayangkan skenario ini saja. Seseorang menghabiskan kurang lebih dua dekade hidupnya untuk bersekolah. Ia bergulat dengan ribuan buku dan artikel ilmiah, menabung stres di balik disertasi yang memeras nalar, dan mungkin pulang dari luar negeri membawa kepakaran yang langka.
Namun, ketika ia menapakkan kaki di ruang prodi, sambutan yang ia terima adalah slip gaji yang angka digitnya sering kali kalah jauh dibanding gaji manajer muda di perusahaan rintisan (startup) yang bahkan belum genap setahun berdiri.
Serikat Pekerja Kampus (SPK) baru-baru ini melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait upah dosen yang banyak di antaranya bahkan tidak menyentuh garis Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini adalah sebuah absurditas yang menyedihkan.
Kita menuntut dosen untuk memproduksi riset kaliber dunia dan melahirkan inovasi yang bisa menyelamatkan ekonomi bangsa, tetapi kita membiarkan mereka berhitung cermat hanya untuk sekadar membayar uang sekolah anaknya atau cicilan KPR mereka.
Ketika kepakaran dihargai lebih rendah dari standar upah minimum buruh pabrik (dengan segala hormat pada profesi buruh), kita sebenarnya sedang mengirim pesan yang sangat jelas kepada talenta terbaik Indonesia: "Jangan jadi dosen, carilah pekerjaan lain yang lebih menghargai kemanusiaanmu."
Permen 52 Tahun 2025: Oase atau Sekadar Ilusi?
Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan "senjata" regulasi baru, yakni Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
Secara sepintas, aturan ini tampak seperti angin segar. Ia hadir menggantikan regulasi lama yang dianggap mencekik dan mencoba memberikan kepastian hukum, terutama bagi rekan-rekan dosen non-ASN yang selama ini menjadi "warga kelas dua" di ekosistem pendidikan tinggi kita.
Penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen swasta menjadi poin yang cukup menarik untuk diperdebatkan. Namun, sebagai orang yang ikut bergelut di dunia pendidikan, saya belajar untuk tidak cepat-cepat bersorak. Sejarah regulasi kita sering kali terjebak dalam sebuah penyakit birokrasi yang gemar menciptakan aturan administratif yang indah di atas kertas, tetapi lumpuh saat berhadapan dengan realitas pendanaan.
Masalahnya, tunjangan profesi bukanlah gaji pokok. Selama gaji pokok dosen masih dianggap sebagai "kerelaan berkorban", tunjangan hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak menyembuhkan penyakit kronis kemiskinan struktural dosen.

 3 hours ago
3
3 hours ago
3