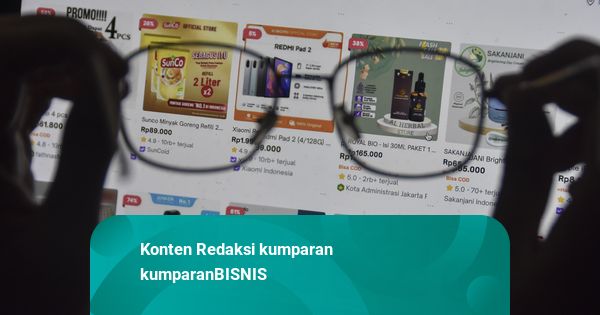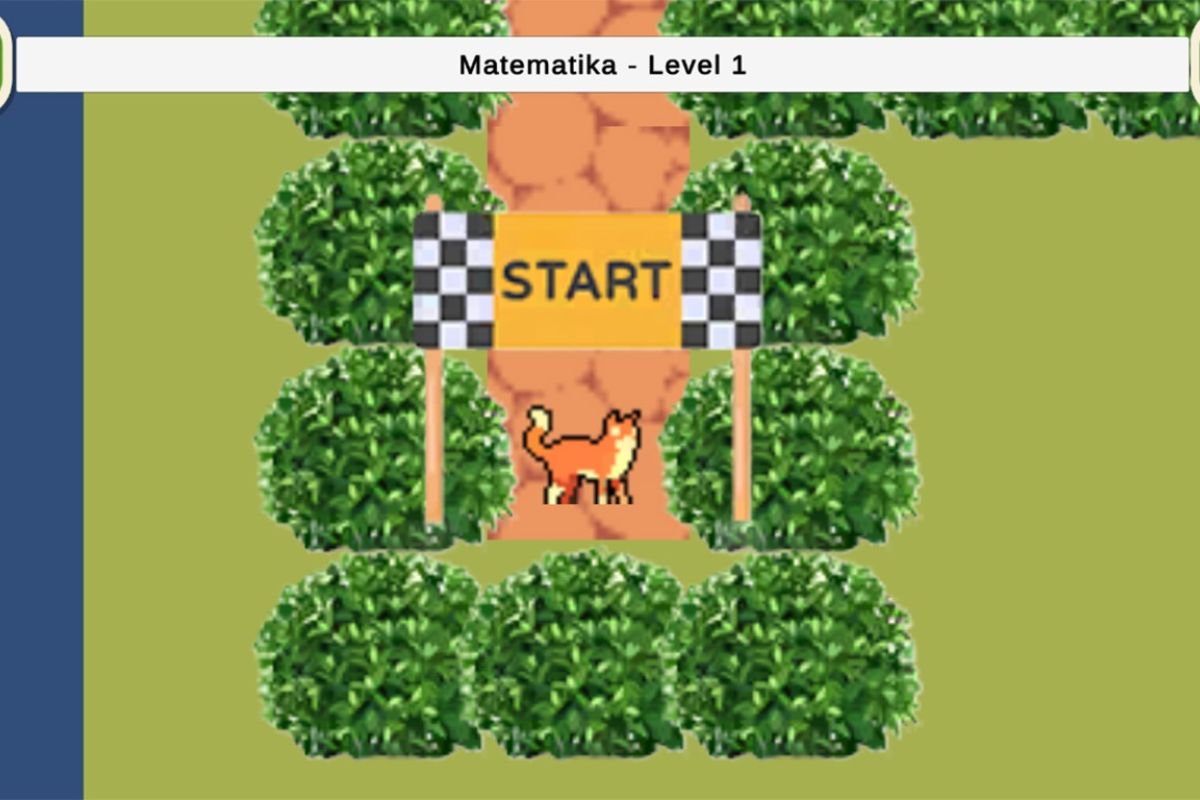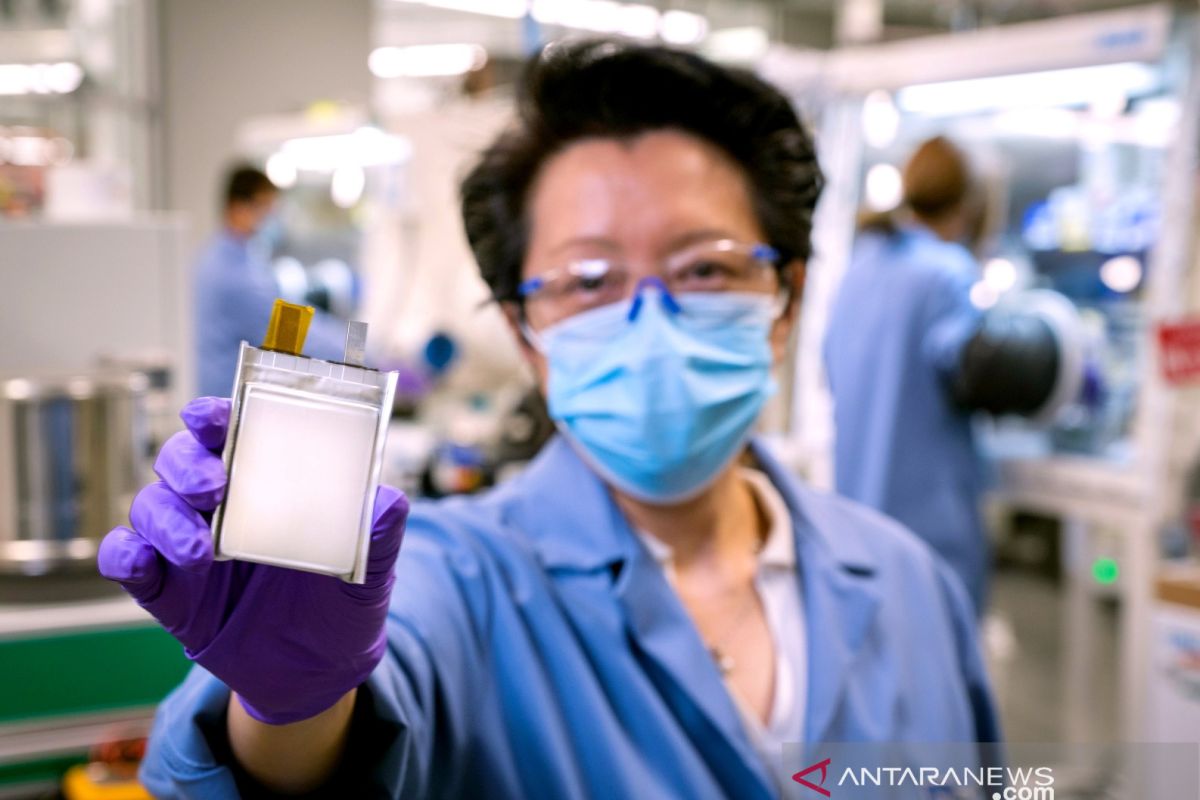Fenomena minimnya literasi mahasiswa Indonesia bukan sekadar kelemahan individu, melainkan cerminan krisis sistemik dalam pendidikan kita. Data global menunjukkan tren serupa: bahkan lulusan universitas di Kanada dan Amerika Serikat mengalami penurunan kemampuan membaca dan bernalar. Maka, kritik terhadap pendidikan Indonesia harus ditempatkan dalam konteks lebih luas, bahwa dunia sedang menghadapi krisis literasi, dan kita tidak kebal.
Literasi Sebagai Fondasi Kehidupan
Saya ingin memulai refleksi ini dari ruang kelas saya sendiri. Mahasiswa yang saya temui sering kali tidak mengenal istilah sederhana seperti detoksifikasi, bencana ekologis, sinergisme, atau intervensi. Kalau istilah saja mereka tak mengerti, bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan nalar dan membangun logika. Mereka miskin kosa kata, nalar sempit, dan logika tidak berjalan. Pertanyaan yang muncul: Apakah ini sekadar kelemahan generasi, atau ada yang lebih dalam?
Saya berpendapat, ada yang salah dengan ekosistem pendidikan kita. Pendidikan Indonesia terlalu lama terjebak dalam obsesi angka, seperti akreditasi, peringkat, sertifikasi, sementara substansi, yaitu kemampuan membaca, menalar, dan berbahasa, dibiarkan merosot.
Fenomena ini bukan unik Indonesia. Literacy Pittsburgh (2023) mencatat bahwa rendahnya literasi di Amerika sering berakar pada faktor sosial: kemiskinan, kurangnya teladan membaca, perpindahan sekolah, hingga trauma komunitas. Dampaknya luas: pengangguran lebih tinggi, produktivitas rendah, bahkan salah penggunaan obat karena tidak mampu memahami informasi kesehatan. Artinya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca, melainkan fondasi kehidupan sosial dan ekonomi.
Di Kanada, sebuah studi menunjukkan bahwa 27% lulusan universitas berusia 25–65 tahun berada pada level literasi rendah (level 2 atau di bawahnya), dan 31% berada di level rendah untuk numerasi (Statistics Canada, 2014). Ironisnya, meski bergelar sarjana, mereka tidak memiliki keterampilan dasar untuk memahami teks kompleks atau melakukan perhitungan sederhana. Saya tidak menggunakan data hasil skor PISA untuk Indonesia untuk tidak menambah miris hati kita.
Urgensi Reformasi Akademik
Dalam laporannya, Clark dan HEQCO (2014) menekankan bahwa bukti penurunan literasi di kalangan lulusan universitas menambah urgensi reformasi akademik. Bukankah ini mirip dengan kondisi kita, di mana mahasiswa datang ke kampus tanpa kebiasaan membaca, tanpa modal kosa kata, dan tanpa tradisi intelektual?
Amerika Serikat pun menghadapi krisis serupa. Harvard Gazette (2025) melaporkan bahwa skor membaca siswa SMA jatuh ke titik terendah sejak 1992. Penurunan ini bukan hanya akibat pandemi, melainkan tren jangka panjang sejak pertengahan dekade 2010-an.
Salah satu penyebab utama adalah menurunnya minat membaca untuk kesenangan: hanya 14% remaja membaca setiap hari untuk hiburan, turun dari 27% pada 2012. Sebaliknya, 31% hampir tidak pernah membaca untuk kesenangan.
Bukankah ini juga terjadi di Indonesia, di mana mahasiswa lebih akrab dengan gawai dan video pendek daripada akrab dengan buku atau artikel hasil penelitian?
Jika kita hubungkan, terlihat pola global: literasi menurun karena ekosistem sosial, digital, dan pendidikan gagal menumbuhkan kebiasaan membaca dan bernalar. Di Indonesia, masalah ini diperparah oleh sistem pendidikan yang menekankan hafalan, ujian seragam, dan akreditasi administratif.
Mahasiswa tidak pernah diajak berhadapan dengan kosa kata baru, tidak pernah dilatih mengaitkan istilah dengan konteks hidup mereka, dan tidak pernah diberi ruang untuk berdebat kritis.
Kita harus mengakui bahwa krisis literasi adalah krisis peradaban. Tanpa kemampuan membaca dan bernalar, masyarakat kehilangan daya kritis terhadap informasi. Di era banjir hoaks, mahasiswa yang miskin kosa kata dan logika akan mudah terjebak dalam manipulasi. Pendidikan yang gagal menumbuhkan literasi berarti menyerahkan generasi muda pada arus informasi tanpa kompas.
Kampus Pun Terjebak
Kampus Indonesia sering kali terjebak dalam ritual administratif. Akreditasi, borang, dan sertifikasi menjadi tujuan utama, sementara substansi pembelajaran diabaikan. Padahal, literasi adalah inti dari semua disiplin ilmu. Mahasiswa teknik, kedokteran, atau pertanian sekalipun membutuhkan kosa kata dan logika untuk memahami teks, menulis laporan, dan berargumentasi. Tanpa itu, gelar akademik hanya menjadi simbol kosong.
Kita perlu menyoroti peran dosen. Dosen bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator literasi. Setiap istilah baru harus dijelaskan, dipraktikkan, dan dihubungkan dengan kehidupan nyata. Mahasiswa harus diajak menulis ulang, berdebat, dan memvisualisasikan konsep. Literasi tidak tumbuh dari ceramah satu arah, melainkan dari interaksi yang menantang nalar.
Kebijakan pendidikan nasional harus bergeser dari obsesi angka ke substansi. Pemerintah harus berani menempatkan literasi sebagai indikator ut...

 5 hours ago
2
5 hours ago
2