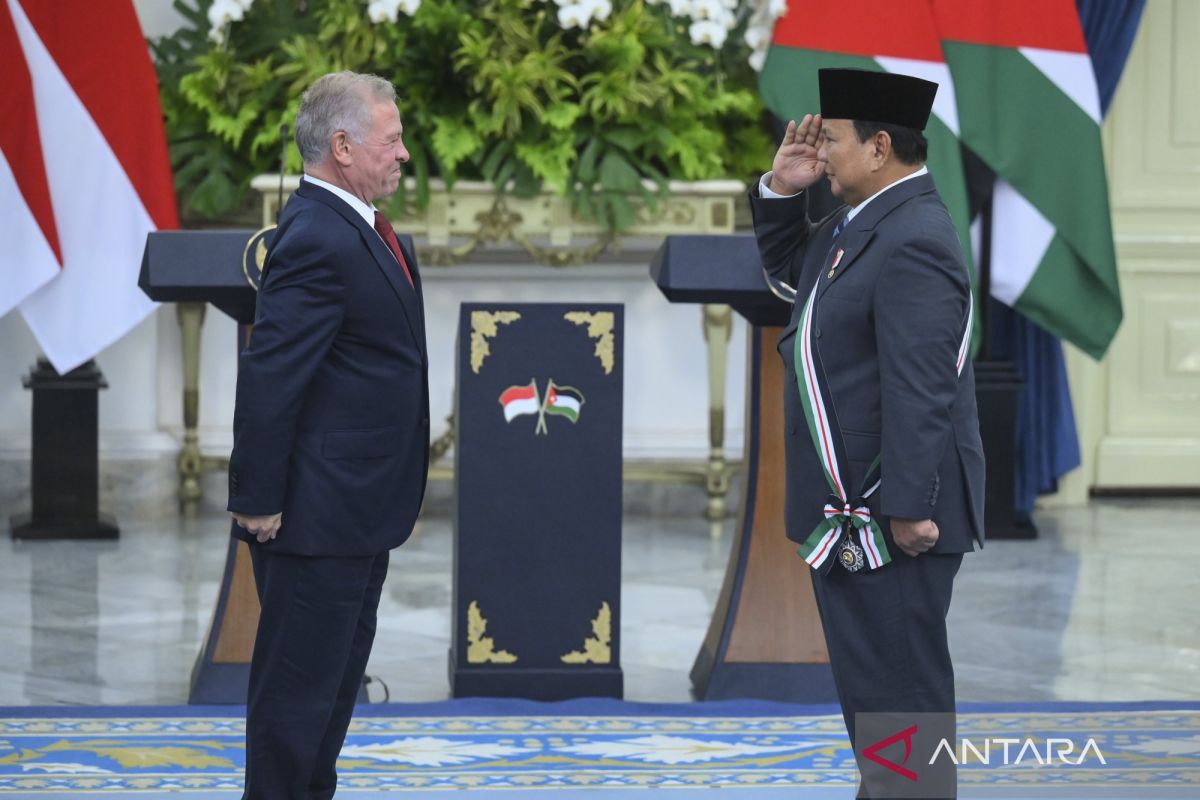Pada menit-menit awal film Pangku (2025), penonton disodorkan visual yang menyayat: seorang perempuan hamil bernama Sartika yang berjalan sendirian di jalur Pantura pada malam hari. Lampu-lampu kendaraan besar melaju cepat melewatinya, seperti dunia yang terus bergerak tanpa peduli apakah ia sanggup mengejarnya atau tidak. Nafasnya berat, langkahnya pelan, dan tatapannya seperti memikirkan lebih banyak hal daripada kata-kata yang sempat ia ucapkan dalam film itu. Ia berjalan bukan karena ingin, tetapi karena hidup mendesaknya untuk terus bergerak. Pada momen itu, ia bukan sekadar karakter film, namun menjadi representasi jutaan perempuan yang hidup dalam ruang antara: bukan miskin secara statistik, tetapi tidak pernah cukup aman untuk merasa hidup.
Fenomena kopi pangku yang menjadi latar cerita film ini bukan sekadar catatan sosial eksotis, melainkan hasil dari sistem ekonomi yang tidak pernah selesai membangun tangga untuk mereka yang paling membutuhkan ruang naik. Sektor informal di Indonesia telah lama menjadi penampung perempuan yang tidak memiliki akses pada pendidikan tinggi, modal usaha, sertifikasi kerja, atau jaringan profesional. Dalam sebuah penelitian sosiologis yang terbit tahun 2020, ditemukan bagaimana tubuh perempuan di ruang-ruang seperti ini perlahan berubah menjadi bahasa transaksi. Bukan identitas, bukan aspirasi, tetapi alat tukar.
Data Badan Pusat Statistik pada 2023 memperlihatkan bahwa sekitar 59 persen pekerja perempuan berada di sektor informal. Namun angka itu hanya menjadi dingin dan abstrak sampai kita meletakkan wajah Sartika di balik angka tersebut. Ia bekerja, tetapi tidak dicatat dalam regulasi ketenagakerjaan. Ia berkontribusi dalam sirkulasi uang, tetapi tidak dianggap layak menerima jaminan sosial. Ia ada dalam pusat aktivitas masyarakat, di pasar, di pinggir jalan, di warung, tetapi tidak pernah benar-benar diakui negara.
Kontrasnya, sejarah Indonesia menyimpan nama-nama perempuan yang dielu-elukan. Salah satu yang paling sering disebut adalah Cut Nyak Dien. Kita merayakan keberaniannya, menempatkan namanya pada buku pelajaran, jalan raya, hingga patung. Namun perayaan itu lebih mirip penghormatan terhadap legenda daripada pewarisan strategi perjuangannya. Cut Nyak Dien memimpin perang dengan jaringan, strategi, negosiasi, dan keberanian. Namun hari ini, perempuan seperti Sartika hanya diberi slogan motivasi, bukan akses pada jaringan yang sama; diberi teladan, bukan metode.
Hal yang sama hadir dalam program-program pemerintah. Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai inisiatif yang ditujukan untuk perempuan: program kredit mikro, pendampingan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan berbasis desa, dan mekanisme bantuan sosial. Beberapa penelitian kebijakan menunjukkan bahwa ada perempuan yang berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan melalui akses permodalan komunitas. Namun banyak evaluasi juga menunjukkan pola yang berulang: program berhenti di permukaan. Pelatihan diberikan, foto dokumentasi diambil, laporan disusun, lalu perempuan kembali sendirian menghadapi pasar yang tidak sabar, kompetisi yang brutal, dan birokrasi yang tidak ramah.
Model pemberdayaan seperti ini mirip rumah yang sudah memiliki fondasi, tetapi tidak pernah diberi dinding. Model pemberdayaan itu terlihat seperti struktur, tetapi tidak dapat dihuni. Perempuan diberi arahan, namun tidak diberi perlindungan; diberi pelatihan, namun tidak diberi jaminan pasar; diberi modal awal, namun dilepas tanpa pendampingan ketika masalah muncul. Banyak perempuan akhirnya kembali ke jalur yang sama, entah kembali menjadi pekerja warung kopi pangku, pekerja rumahan tanpa perlindungan, atau pekerja migran yang masuk sektor risiko tinggi.
Negara-negara lain pernah melalui pola yang sama. Di Thailand, upaya penertiban moral atas industri yang melibatkan tubuh perempuan tidak pernah menghasilkan transformasi berarti selama tidak diikuti ekosistem pendukung. Filipina pernah mencoba pendekatan serupa melalui kombinasi regulasi moral dan legalisasi sebagian praktik. Namun perubahan yang paling nyata muncul ketika akses pendidikan, kredit komunitas, perlindungan hukum dan pendampingan usaha dilakukan sebagai sistem, bukan sebagai proyek.
Pada akhirnya, persoalan perempuan marjinal tidak pernah sederhana. Ia tidak berdiri pada satu faktor, tetapi pada simpul antara ekonomi, norma sosial, birokrasi akses, pasar tenaga kerja, dan struktur keluarga. Kita sering mengatakan perempuan harus maju, tetapi di saat yang sama kita membatasi langkah mereka. Kita meminta mereka mandiri, tetapi kita biarkan mereka mencari jalan di tanah yang retak tanpa kompas. Kita menginginkan mereka bangkit, tetapi yang kita berikan hanyalah poster motivasi, bukan struktur yang bisa dipanjat.
Jika perempuan seperti Sartika sungguh ingin keluar dari ruang liminal ini, yang dibutuhkan bukan instruksi, tetapi infrastruktur. Bukan sekadar hibah, tetapi sistem yang memberi kesempatan kedua dan ketiga. Sistem yang menyediakan ruang aman untuk jatuh tanpa menempelkan stigma permanen. Sistem yang bekerja tidak pada logika belas kasihan, tetapi pada prinsip keadilan.
Pemberdayaan sejati bukan tentang menyuruh seseorang berdiri. Pemberdayaan adalah menciptakan dunia di mana berdiri menjadi mungkin. Ketika film Pangku berakhir, wajah Sartika kembali menjadi titik fokus. Masih dengan diam itu, diam yang bukan pasrah, tetapi diam yang memendam pertanyaan: apakah saya memilih nasib ini, atau sistem yang memaksa saya demikian?
Jika suatu hari warung kopi pangku tidak lagi menjadi tempat perempuan bertahan hidup, itu berarti bukan mereka yang menghilang, tetapi sistem yang akhirnya berubah bentuk. Bentuk kehidupan perempuan marjinal hari ini memang terlihat seperti garis fraktal: tampak acak, retak, tidak teratur. Namun fraktal selalu memiliki pola tersembunyi. Pola yang muncul bukan dari nasib, tetapi dari struktur. Struktur itu, berbeda dengan nasib, selalu bisa diubah.

 1 month ago
28
1 month ago
28