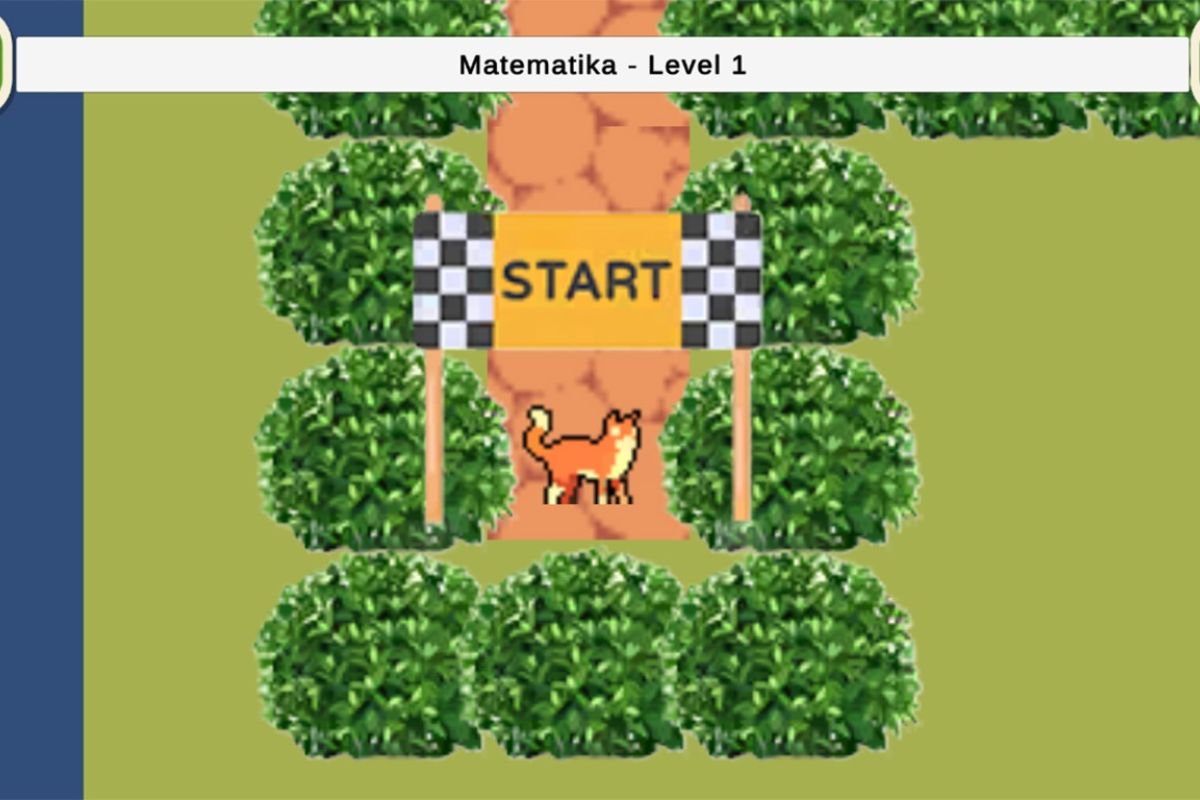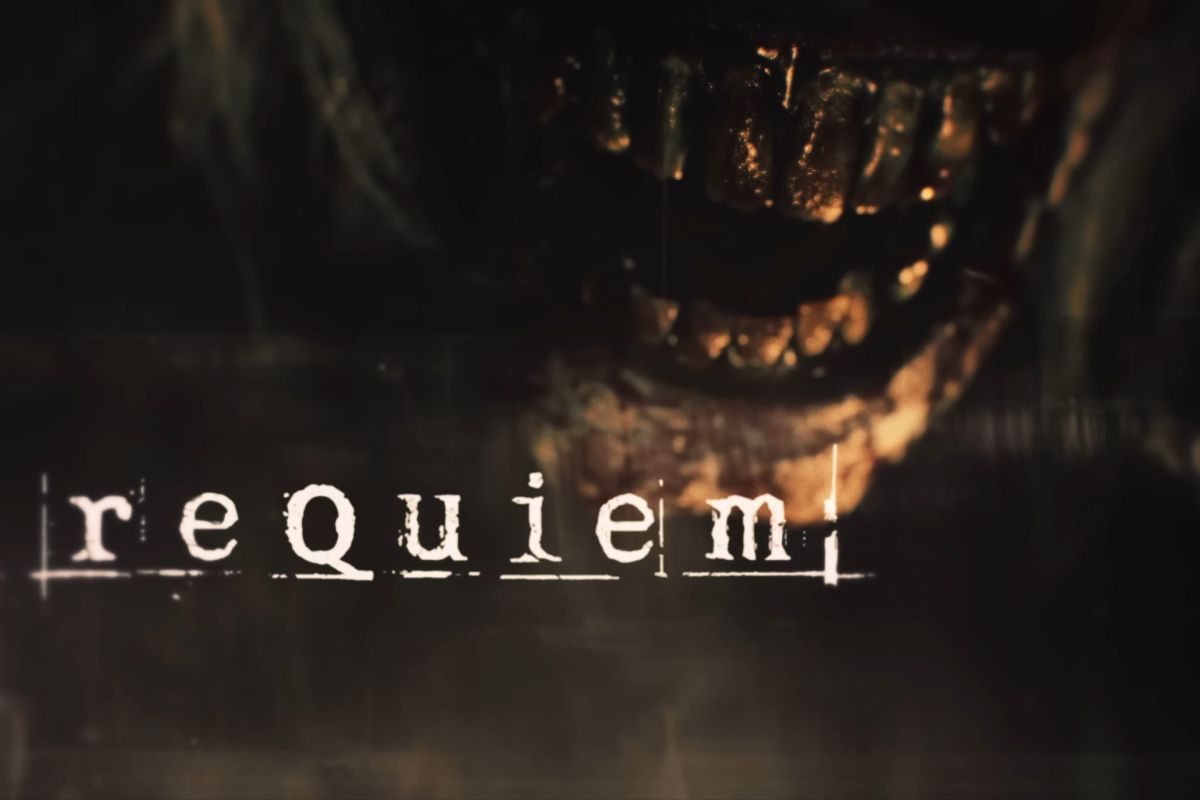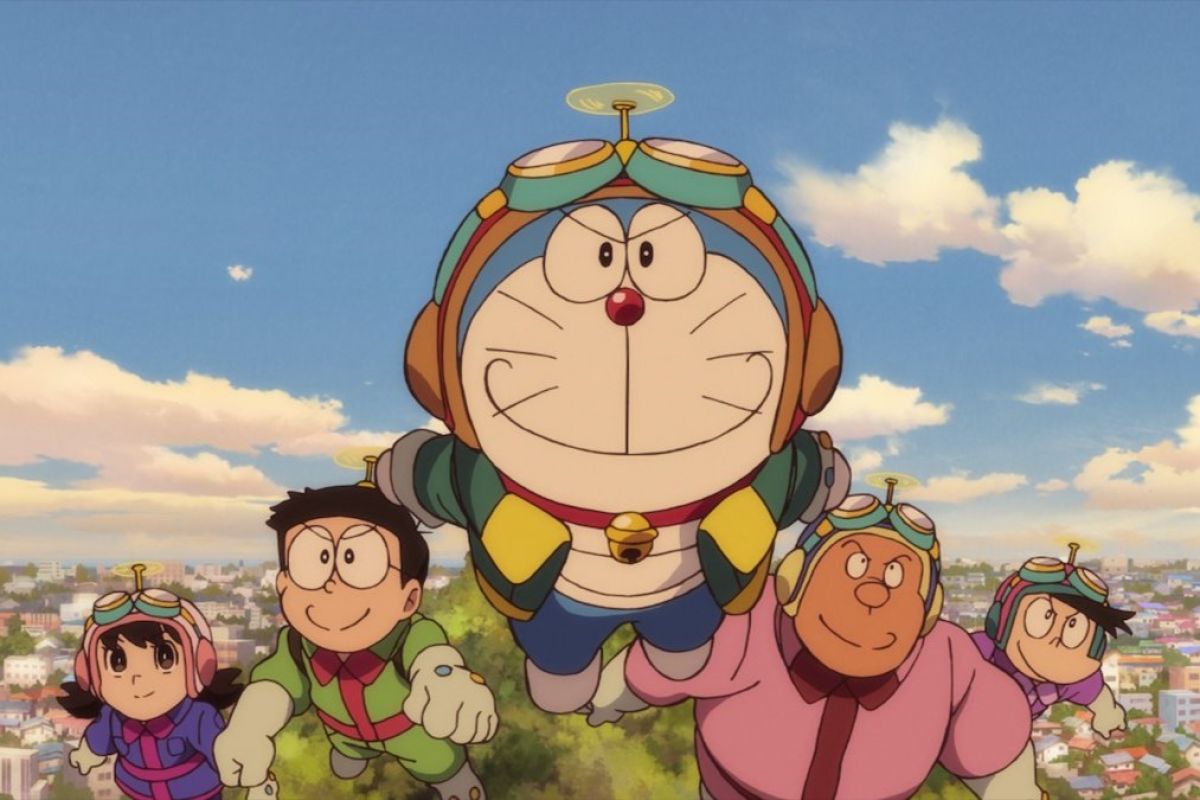Narasi pembangunan ekonomi terus didengungkan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Di sisi lain, krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup semakin nyata terlihat. Pengrusakan ekosistem terjadi dalam skala yang mengkhawatirkan. Sudah beribu-ribu teori pembangunan lahir, tapi tidak ada satupun yang berhasil mengatasi kontradiksi ini. Di tengah kondisi ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah konstitusi kita, khususnya Pasal 33 UUD 1945, memiliki relevansi dalam merespons krisis ekologis kontemporer?
Pasal 33 UUD 1945 selama ini sering dipahami secara sempit sebagai pasal yang mengatur sistem ekonomi nasional. Pembacaan yang sempit ini telah menyebabkan esensi filosofis pasal tersebut terabaikan. Padahal, sebagai philosophische grondslag perekonomian Indonesia, Pasal 33 bukan sekadar instrumen teknikal, melainkan manifestasi konkret dari Pancasila, khususnya Sila Kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Ketika kita membaca Pasal 33 dengan kacamata yang lebih holistik, khususnya melalui perspektif ekologi kritis dan pendekatan transkonstruktif, akan tampak bahwa pasal ini sesungguhnya mengandung potensi emansipatoris untuk merumuskan keadilan sosial-ekologis di Indonesia.
Berangkat dari keresahan akan premis bahwa Pasal 33 UUD 1945 hanya dimaknai soal koperasi semata, menuntut kita pada pembacaan yang lebih holistik daripada itu. Oleh karena itu, diperlukan cara berpikir baru melalui lensa ekologi kritis dan pendekatan transkonstruktif. Pendekatan ini memungkinkan kita mengeksplorasi bagaimana Pasal 33 menjadi basis untuk memosisikan seluruh rakyat Indonesia sebagai subjek ekologi yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
Pasal 33 UUD 1945: Bukan Sekadar Ekonomi Semata
Untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 secara utuh, kita perlu melampaui pembacaan yang mereduksinya sebagai pasal tentang ekonomi (baca: koperasi) semata. Pasal 33 dalam rumusannya yang asli berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jika kita mencermati rumusan ini, akan tampak bahwa Pasal 33 tidak hanya berbicara tentang mekanisme ekonomi, tetapi tentang prinsip-prinsip filosofis yang mendasari hubungan antara manusia, negara, dan alam. Ayat pertama tentang "asas kekeluargaan" menunjukkan penolakan terhadap individualisme ekonomi liberal dan kolektivisme yang menekan individu. Ayat kedua tentang penguasaan negara atas cabang produksi penting menunjukkan komitmen pada keadilan distributif. Sementara ayat ketiga, yang paling relevan dengan diskusi ekologis, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam "dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Frasa "usaha bersama" dan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" inilah yang menjadi kunci untuk memahami Pasal 33 sebagai philosophische grondslag. Kemakmuran di sini tidak boleh dipahami dalam pengertian materialistis semata, melainkan sebagai kesejahteraan holistik yang mencakup keseimbangan sosial, kultural, dan ekologis. Pemahaman ini sejalan dengan spirit Pancasila, khususnya Sila Kelima yang menekankan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak mungkin terwujud tanpa keadilan ekologis, karena kehancuran lingkungan selalu menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok marjinal.
Mohammad Hatta, sebagai salah satu arsitek Pasal 33, pernah menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan gotong royong dan kebersamaan, bukan kompetisi individualistis. Gotong royong, dalam konteks ekologis di Indonesia, dapat dipahami sebagai prinsip hubungan resiprokal antara manusia dengan alam. Alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan mitra dalam sistem kehidupan yang saling bergantung. Sehingga, Pasal 33 sebenarnya mengandung bibit pemikiran ekologis yang mendahului wacana lingkungan global kontemporer.
Ekologi Kritis dan Pasal 33
Untuk membedah potensi emansipatoris Pasal 33 dalam konteks ekologis, kita memerlukan kerangka analisis yang mampu melampaui pembacaan positivistik. Di sinilah ekologi kritis dan pendekatan transkonstruktif menjadi relevan. Ekologi kritis adalah aliran pemikiran yang tidak hanya menganalisis krisis lingkungan dari sisi teknis-natural, tetapi juga mengkaji relasi kuasa, struktur ekonomi-politik, dan konstruksi sosial-kultural yang menghasilkan krisis tersebut.
Dengan menggunakan lensa ekologi kritis, kita dapat melihat bahwa interpretasi dominan terhadap Pasal 33 selama ini adalah hasil dari konstruksi ideologis tertentu. Rezim developmentalis, misalnya, menafsirkan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai justifikasi untuk eksploitasi masif sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi. Hutan dibabat untuk memberikan konsesi kepada produsen kayu dan perkebunan, pertambangan diperluas tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, dan masyarakat adat dipinggirkan atas nama "pembangunan nasional". Semua ini dilakukan dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 33.

 3 weeks ago
16
3 weeks ago
16