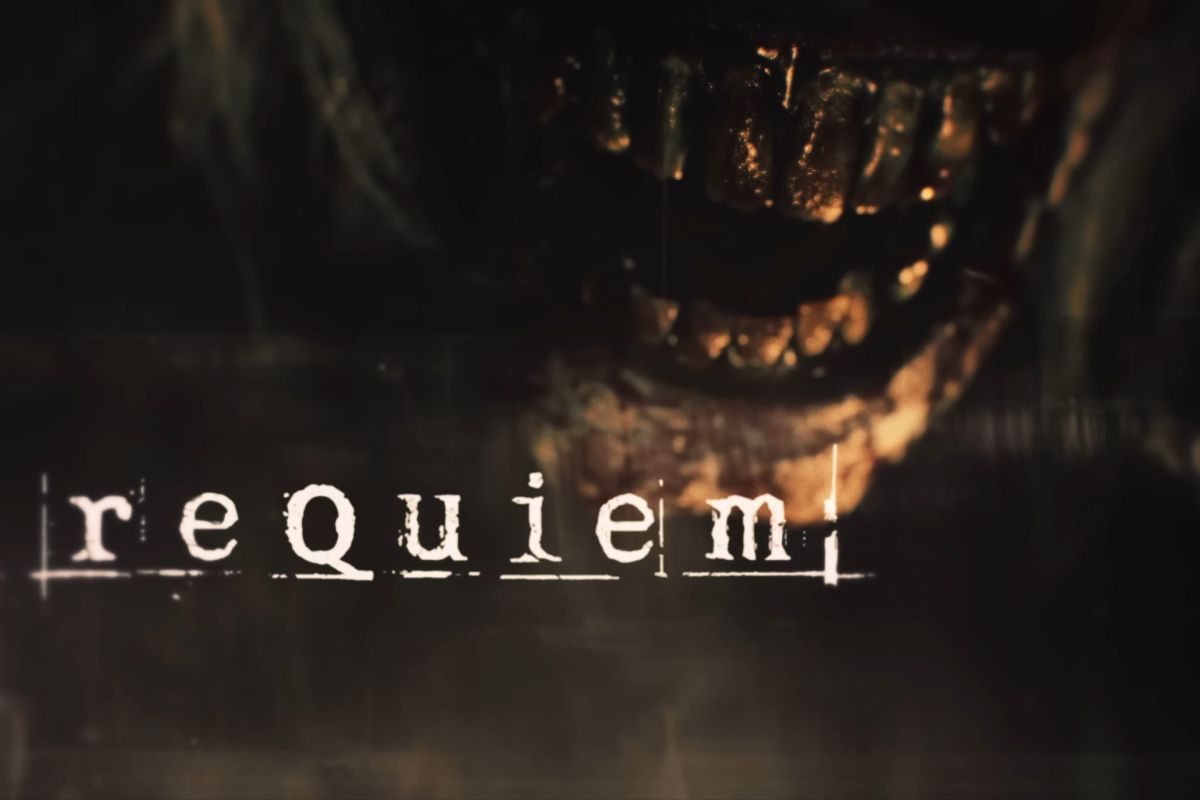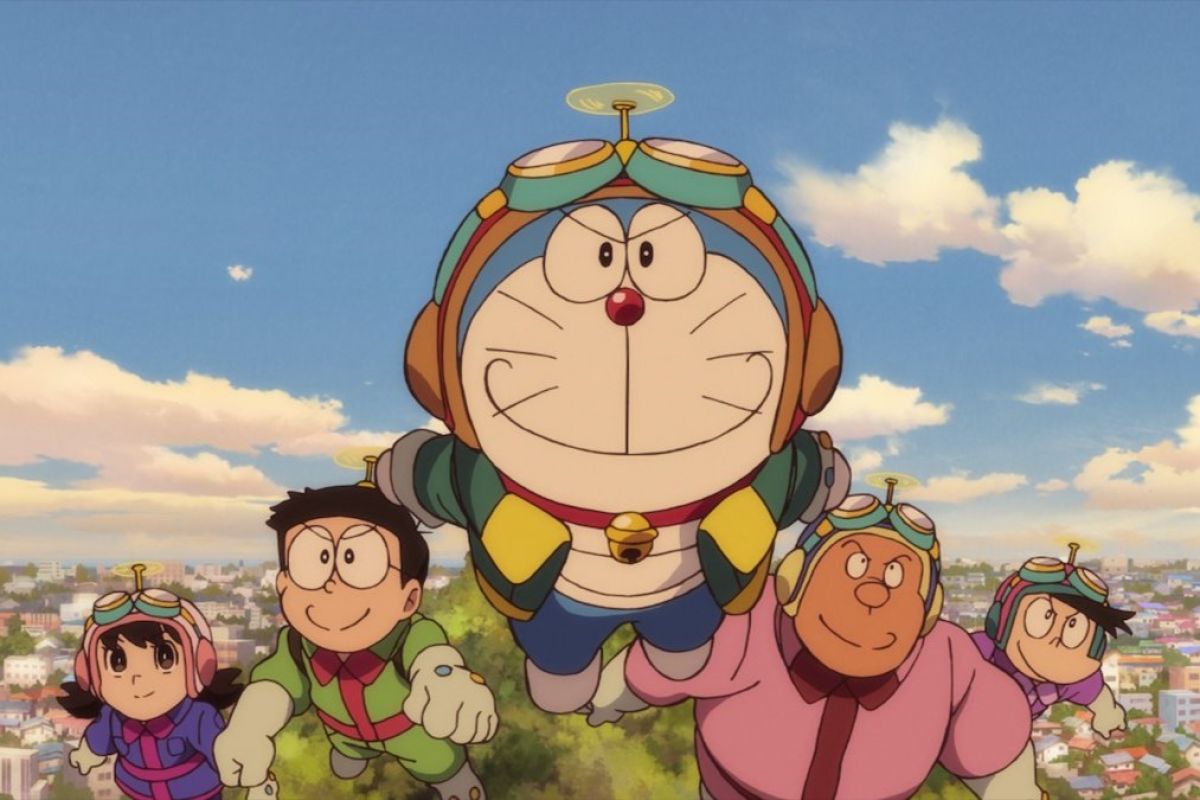Ada kalimat yang terasa seperti kaca bening: tidak memukul, tetapi memantulkan wajah. “Orang pintar merenung, orang bodoh tersinggung.” Kalimat ini bukan untuk menghina orang, melainkan untuk menguji kualitas batin sebuah ekosistem kekuasaan: apakah ia matang menghadapi kritik, atau rapuh mudah tersulut, mudah mengamuk, dan sibuk memburu siapa yang “berani berbeda”.
Negara yang sehat memerlukan dua hal sekaligus: orang yang bekerja dan orang yang berpikir. Orang yang bekerja menjaga mesin berjalan. Orang yang berpikir menjaga arah tetap benar. Ketika meritokrasi runtuh, dua peran ini ikut rusak: yang berkualitas tersingkir, yang tidak cakap naik ke panggung; lalu kritik diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai alarm keselamatan.
Saat Meritokrasi Ditanggalkan, Negara Menanggung Biaya Kebodohan
Meritokrasi bukan slogan manajemen modern. Ia prinsip keadilan: memberi amanah kepada yang layak. Al-Qur’an meletakkan fondasinya dengan tegas:
Saat amanah tidak diberikan kepada ahlinya, negara memasuki fase yang berbahaya: kebijakan dipimpin oleh ketidakcakapan. Dampaknya berantai: lambat membaca perubahan, gagap menghadapi krisis, bingung menetapkan prioritas, lalu menutup kekurangan dengan pencitraan. Pada titik itu, rakyat bukan sekadar menunggu layanan—rakyat menanggung akibat.
Kualitas kepemimpinan selalu terlihat ketika badai datang. Jika pemimpin hanya kuat di podium, tetapi lemah di lapangan, yang terjadi ialah paradoks memalukan: negara kalah tanggap dibanding relawan. Relawan bergerak karena nurani. Negara seharusnya bergerak karena kewajiban.
Orang Kompeten yang Disingkirkan Tidak Pernah Benar-Benar Diam
Ketika orang berkapasitas, berintegritas, dan berpengalaman tidak dimanfaatkan, itu bukan berarti mereka selesai. Banyak dari mereka memilih jalur yang lebih sunyi: merenung, berdiskusi, menulis, mengingatkan, mengkritik—demi menjaga bangsa tetap waras.
Dalam perspektif iman, perenungan bukan kemewahan intelektual. Ia bentuk tanggung jawab moral: menimbang, tabayyun, dan menolak ikut arus kebohongan. Al-Qur’an memerintahkan verifikasi informasi:
Kritik konstruktif lahir dari disiplin nalar dan disiplin iman. Ia bukan “nyinyir”. Ia justru upaya menyelamatkan negara dari keputusan yang keliru, dari proses yang tidak akuntabel, dan dari kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil.
Kematangan Kepemimpinan Diukur dari Cara Menerima Kritik
Pemimpin yang kuat tidak alergi terhadap kritik. Pemimpin yang lemah biasanya punya refleks yang sama: tersinggung dulu, berpikir belakangan. Padahal, kritik yang konstruktif adalah salah satu bentuk “rem” agar kendaraan negara tidak melaju ke jurang.
Al-Qur’an menggambarkan ciri kepemimpinan moral lewat sikap rendah hati dan kesiapan mendengar: “…dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka…” (QS. Asy-Syūrā [42]: 38). Musyawarah bukan formalitas rapat. Musyawarah adalah kesiapan batin untuk menerima masukan yang tidak enak, tetapi benar.
Lebih tajam lagi, Al-Qur’an mengingatkan agar tidak mengolok atau merendahkan pihak lain—karena bisa jadi yang dianggap kecil justru lebih bermartabat:
Kritik bukan penghinaan. Kritik adalah bentuk kepedulian yang belum putus. Yang berbahaya bukan kritik, melainkan silence kolektif—ketika orang baik memilih diam karena takut.
Ketika Relawan Suruhan dan Penjilat Menjadi “Pasukan Tersinggung”
Ada fenomena yang paling merusak: bukan sekadar pemimpin yang alergi kritik, melainkan ekosistem yang memelihara “pasukan tersinggung”. Mereka bukan pembela negara, melainkan pembela posisi. Mereka bekerja bukan untuk kebenaran, melainkan untuk kedekatan. Ketika kritik muncul, responsnya bukan argumen, melainkan intimidasi.

 4 weeks ago
39
4 weeks ago
39