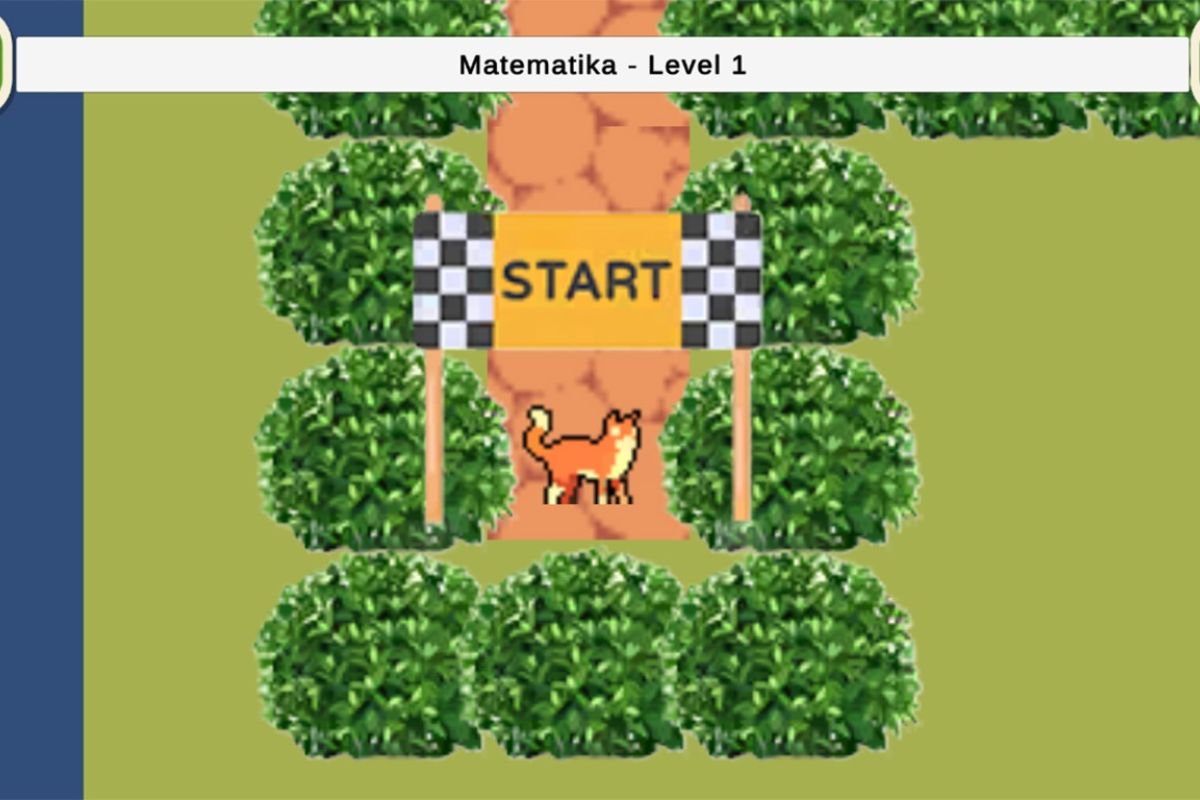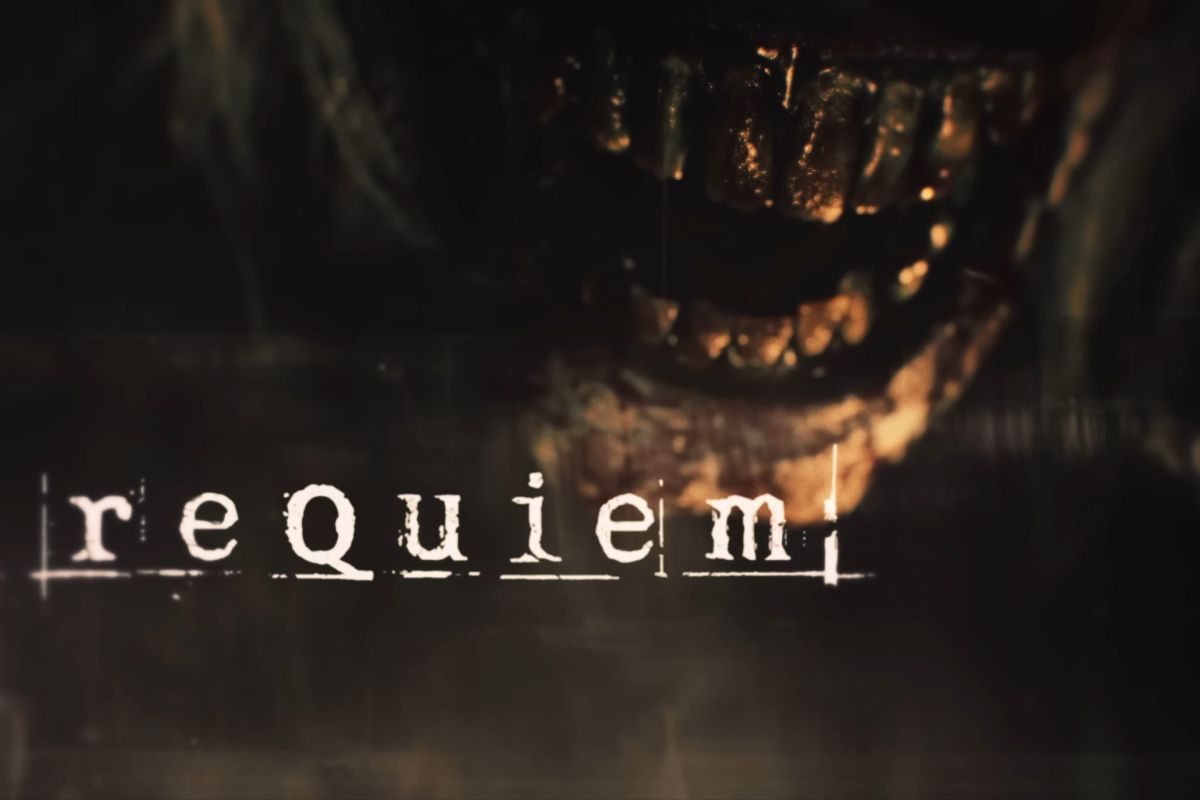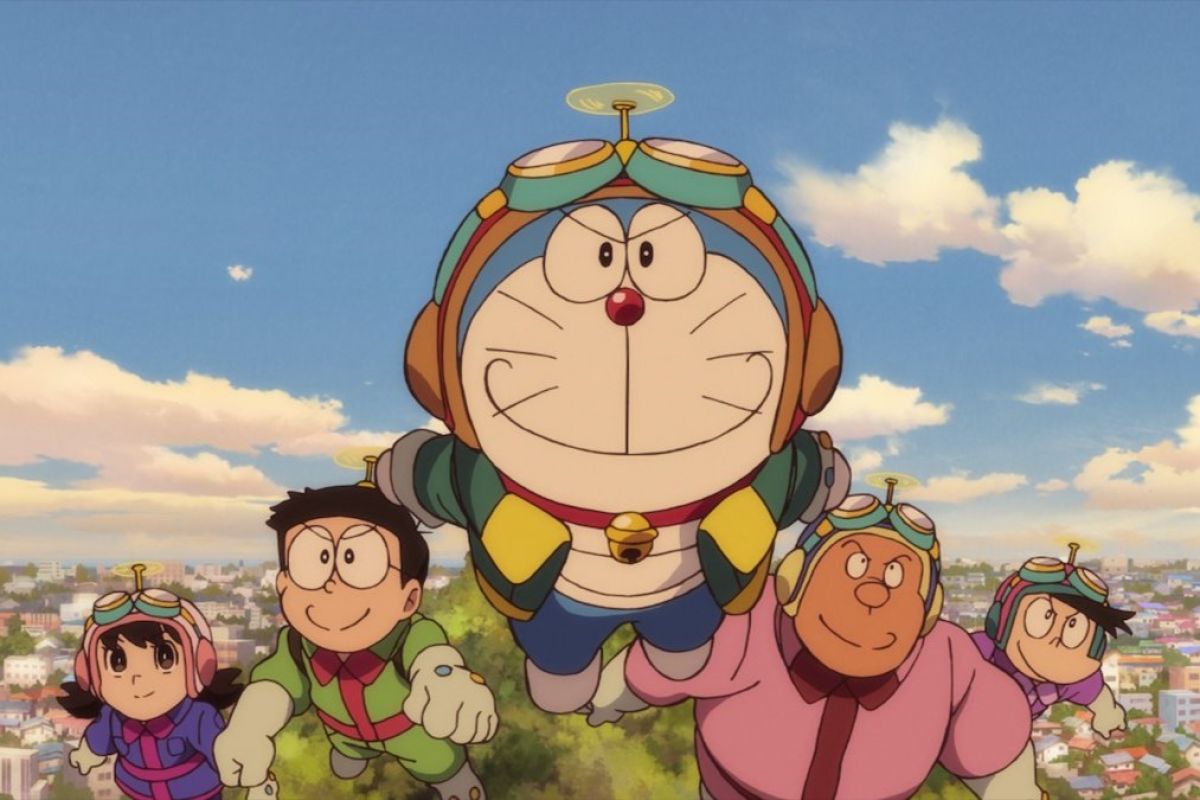“Kenapa sih anak sekarang lebih nyaman curhat ke teman, pasangan, atau bahkan media sosial, dibanding ke orang tuanya sendiri?” Pertanyaan ini sering muncul, namun jarang benar-benar dibahas dari sudut pandang anak.
Ketidaknyamanan anak untuk bercerita kepada orang tua bukanlah tanda kurangnya kasih sayang. Dalam banyak kasus, hal ini justru berakar dari pola komunikasi dan emosi yang belum selesai sejak kecil.
Salah satu penyebab utama adalah rasa takut dihakimi. Tidak sedikit anak yang mencoba berani membuka suara untuk bercerita justru disambut dengan ceramah panjang, perbandingan dengan orang lain, atau respons yang mengecilkan perasaannya. Alih-alih merasa didengar, anak merasa salah sejak awal.
Selain itu, orang tua mungkin lebih fokus pada solusi daripada empati. Padahal, tidak semua cerita membutuhkan nasihat. Banyak anak hanya ingin dipahami, bukan diarahkan. Ketika setiap keluhan selalu diakhiri dengan “harusnya kamu…” atau “makanya dari awal…”, anak belajar bahwa bercerita hanya akan menambah beban.
Faktor lain yang menyebabkan anak sulit percaya adalah kurangnya kehadiran secara emosional. Orang tua bisa saja hadir secara fisik, tetapi tidak secara emosional—sibuk, lelah, atau tidak benar-benar memberi ruang aman untuk anak mengekspresikan dirinya. Dalam kondisi seperti ini, anak memilih diam karena merasa ceritanya tidak penting.
Pengalaman masa lalu juga turut berperan besar. Anak yang pernah dikhianati kepercayaannya—ceritanya disebarkan, dirahasiakan setengah hati, atau dijadikan bahan lelucon meski maksud dari orang tuanya hanya untuk bahan bercandaan—akan membangun dinding ketakutan. Sekali rasa aman runtuh, butuh waktu lama untuk sembuh.
Tidak jarang pula anak tumbuh dalam budaya keluarga yang menormalisasi kalimat seperti “anak tidak boleh membantah” atau “orang tua selalu benar”. Pola ini membuat anak belajar bahwa kejujuran dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan, adalah bentuk pembangkangan.
Bagaimana Agar Komunikasi Anak dan Orang Tua Bisa “Cocok”?
Pertama, orang tua perlu belajar hadir tanpa langsung menghakimi.
Banyak anak berhenti bercerita bukan karena masalahnya besar, tapi karena respons pertama orang tua sering berupa ceramah, perbandingan, atau menyalahkan. Padahal, anak yang bercerita tanpa dipotong pembicaraannya saja mereka merasa sudah cukup.
Kedua, dengarkan perasaan, bukan hanya masalahnya.
Saat anak berkata “aku capek”, yang dibutuhkan bukan solusi instan, melainkan validasi sederhana seperti, “pasti hari ini berat ya buat kamu.” Dari sini, anak belajar bahwa emosinya aman untuk dibagikan.
Ketiga, kurangi kalimat yang membuat anak merasa kecil seperti “kamu selalu…”, “dari dulu kamu memang…”.
Kalimat semacam ini membuat anak merasa dicap, bukan dipahami. Sekali anak merasa dilabeli, keinginan untuk terbuka akan perlahan menghilang.
Keempat, jaga kepercayaan.
Cerita anak bukan konsumsi keluarga besar, bukan bahan candaan, dan bukan alat pembanding. Ketika rahasia anak bocor, yang rusak bukan hanya komunikasi—tetapi juga rasa percaya.

 1 month ago
54
1 month ago
54