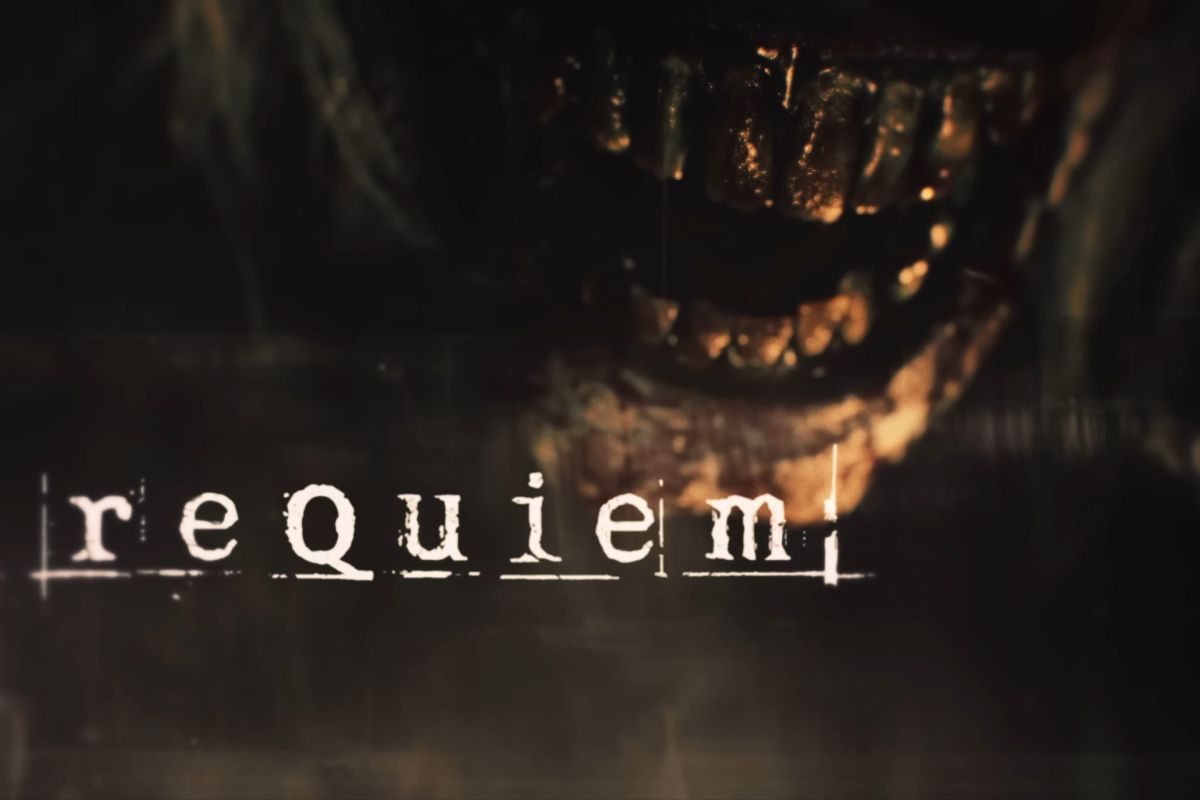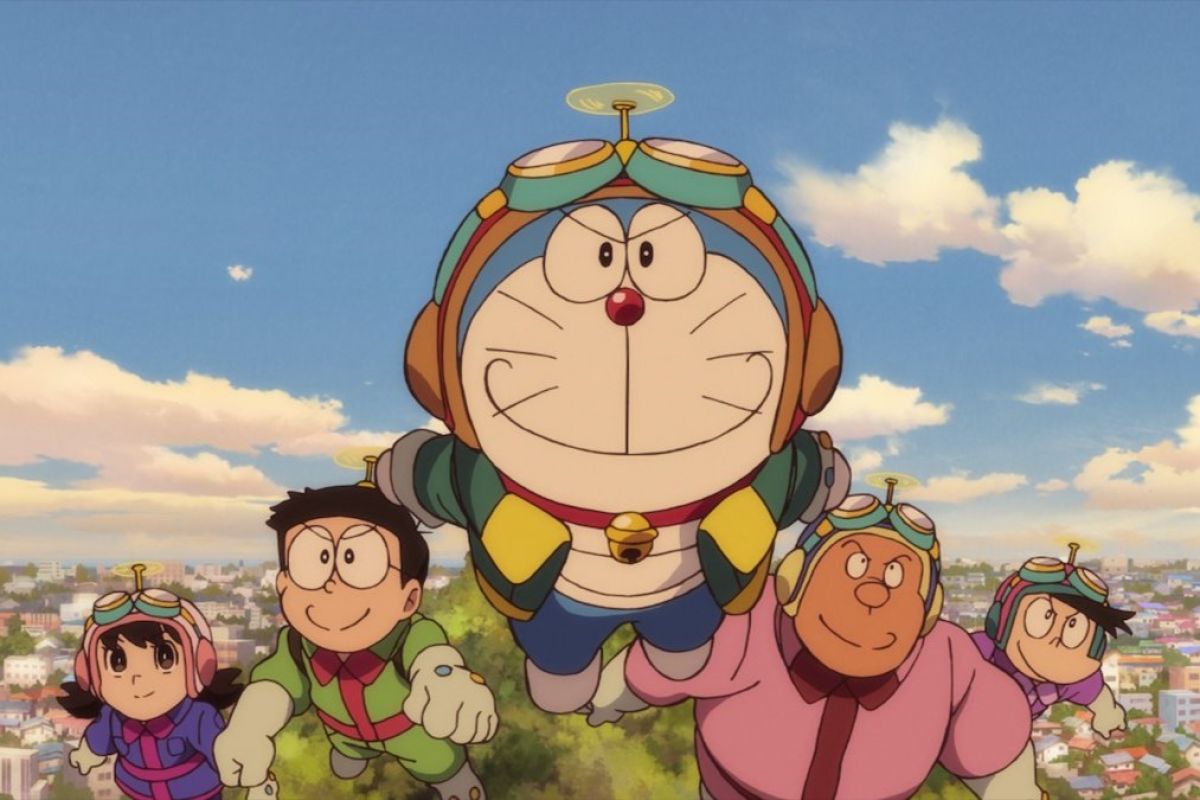Beberapa waktu lalu, saya duduk di sebuah kedai kopi yang penuh sesak oleh mahasiswa. Di meja sebelah, sekelompok anak muda sedang berdiskusi seru tentang tugas kuliah. Namun, ada satu hal yang mengusik telinga: hampir di setiap jeda kalimat, terselip kata "anjir", "anjing", hingga berbagai kebun binatang dan istilah kotor lainnya. Menariknya, mereka mengucapkannya dengan wajah datar, tanpa rasa bersalah, bahkan diselingi tawa renyah.Fenomena ini memicu pertanyaan besar: Sejak kapan makian bertransformasi menjadi tanda titik dan koma dalam percakapan generasi terpelajar kita?
Pergeseran Makna: Dari Amarah Menjadi Akrab
Dulu, kata-kata kasar adalah "peluru" yang dilepaskan hanya saat seseorang berada di puncak amarah atau dalam konflik fisik. Mengucapkannya di depan umum adalah tabu, dan melakukannya di lingkungan akademik adalah "bunuh diri" sosial.
Namun, hari ini kita melihat pergeseran semantik yang luar biasa. Bagi mahasiswa masa kini, kata "anjir" atau "bangsat" sering kali kehilangan taringnya sebagai umpatan. Kata-kata tersebut telah mengalami normalisasi. Ia beralih fungsi menjadi filler words (kata pengisi) atau penanda keakraban (solidarity marker). Semakin kasar panggilannya, seolah semakin tinggi tingkat kedekatan mereka.
Media sosial memainkan peran besar dalam orkestra ini. Konten kreator hingga influencer papan atas sering kali menggunakan bahasa "blak-blakan" tanpa sensor untuk terlihat otentik dan merakyat. Mahasiswa, sebagai konsumen utama konten digital, secara tidak sadar menyerap gaya komunikasi ini ke dalam kehidupan nyata.
Masalahnya adalah ketika batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Jika di tongkrongan bahasa ini dianggap "biasa", maka tanpa sadar ia akan terbawa ke forum yang lebih formal. Kita mulai kesulitan membedakan mana bahasa untuk bersenda gurau dengan teman satu kost, dan mana bahasa yang pantas digunakan dalam diskusi kelas atau saat berhadapan dengan dosen.
Krisis Artikulasi atau Sekadar Tren?
Ada kekhawatiran bahwa penggunaan bahasa kotor yang berlebihan mencerminkan kemiskinan diksi. Ketika seseorang tidak mampu mengekspresikan rasa kagum, mereka menyebut "Anjir, keren banget!". Ketika kecewa, "Anjir, parah banget!".
Kata "anjir" seolah menjadi alat serbaguna yang menggantikan kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Padahal, sebagai mahasiswa—kaum intelektual yang diharapkan menjadi penjaga peradaban—kemampuan mengolah kata dan rasa seharusnya menjadi senjata utama.
Menimbang Kembali Etika Berbahasa
Tentu, kita tidak bisa sekadar melarang atau bersikap puritan. Bahasa itu dinamis dan akan selalu berubah mengikuti zaman. Namun, normalisasi bahasa kotor yang tidak terkontrol bisa mengikis rasa hormat dan etika berkomunikasi.
Menjadi "asik" dan "gaul" tidak harus dengan menggadaikan kesantunan. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa kampus bukan sekadar tempat mengejar IPK, tapi juga tempat menyemai karakter. Jika bahasa yang keluar dari mulut kaum terpelajar saja sudah kehilangan "filternya", lantas apa yang bisa kita harapkan dari wajah komunikasi bangsa ini di masa depan?
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadikan makian sebagai bumbu wajib. Sebab, keakraban yang sejati tidak dibangun dari seberapa kasar kita memanggil teman, tapi dari seberapa berkualitas isi pembicaraan kita.

 1 month ago
41
1 month ago
41