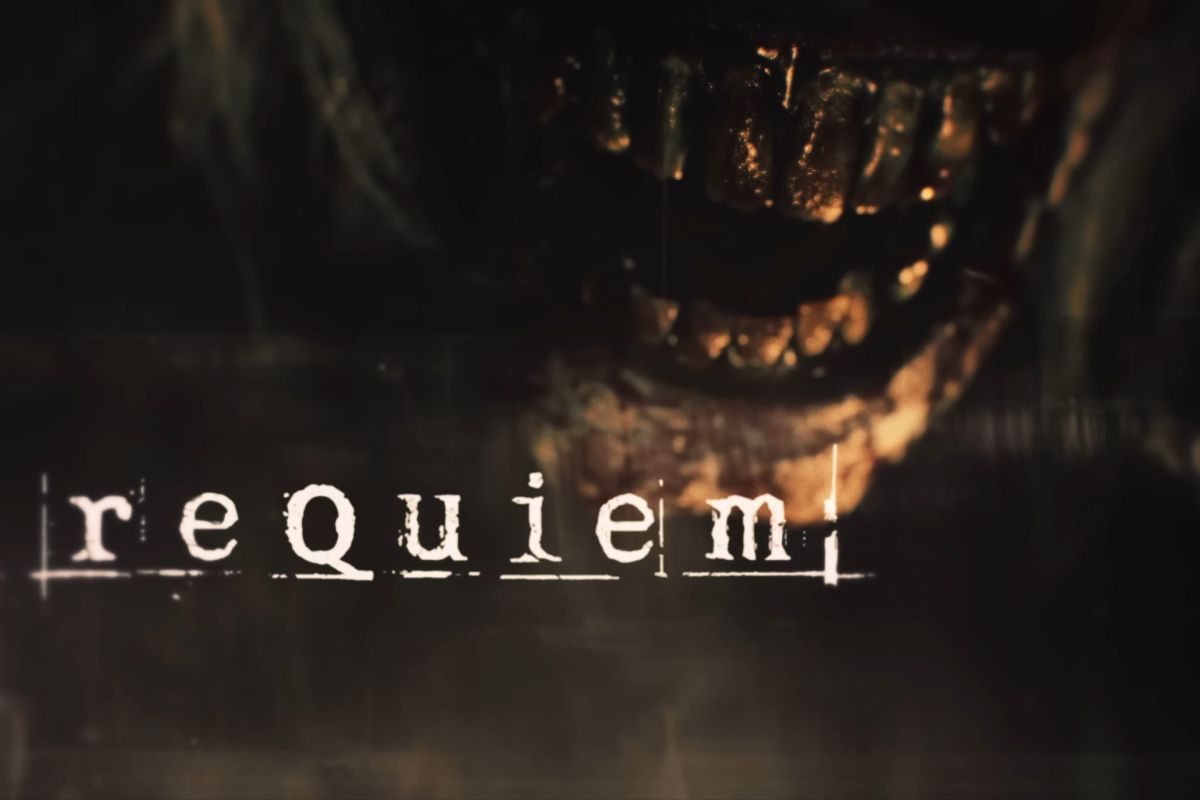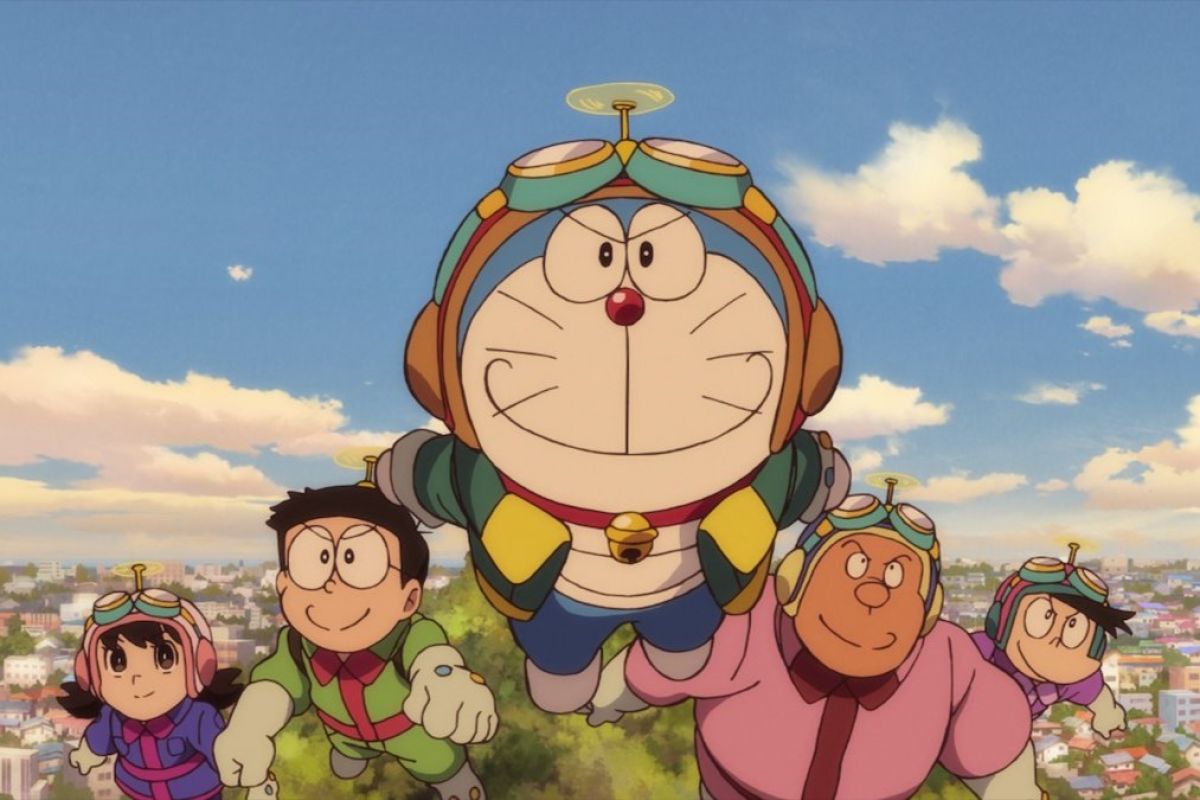"Borobudur itu sakral, Bung! Dibandingkan dengan Batu Caves, itu tidak apple to apple!"
Begitu bunyi protes di kolom komentar saya. Seolah-olah membandingkan Borobudur dengan Batu Caves adalah dosa tak terampuni. Lho, tunggu dulu. Anda kira Batu Caves itu sekadar pasar malam yang kebetulan ada patungnya?
Bagi jutaan umat Hindu, gua batu kapur di Selangor itu sama sucinya dengan Candi Borobudur bagi umat Buddha. Bedanya cuma satu. Mentalitas pengelolanya. Kita hobi menjadikan 'kesakralan' sebagai tameng birokrasi yang menjauhkan candi dari rakyat, sementara Malaysia justru berhasil 'menikahkan' kesakralan dengan komersialisasi tanpa drama.
Lihat saja di sana. Eskalator modern dan tangga warna-warni instagramable bisa hidup rukun berdampingan dengan altar doa yang khusyuk. Tamparan keras bagi kita. Ini bukti bahwa wisata tak menodai kesucian, tapi justru membiayainya.
Sudahlah, kita simpan dulu perdebatan soal 'apple to apple' itu. Anggap saja kisah Batu Caves baru babak pemanasan. Karena pengalaman yang akan saya ceritakan ini, jaminannya bakal menampar ego pariwisata kita jauh lebih keras.
Usai liputan Festival Thaipusam, skenario saya sebenarnya sederhana. Pulang. Koper sudah terkunci. Tiket siap dipesan. Tapi Helmi, kawan Malaysia saya yang lidahnya memang 'berbisa' itu, mendadak memveto keputusan saya.
"Jangan balik dulu, Fit," cegahnya sambil menyeringai. "Kau belum sah injak Kuala Lumpur kalau belum ke Bukit Bintang".
"Duit menipis, Bos. Di sana mahal," tolak saya halus.
"Ah, tenang. Ada sepupu aku. Dia 'Sultan'. Namanya Rizal Hakim bin Abdul Zakir," jawab Helmi enteng.
Mendengar nama 'Hakim', nyali saya ciut. Saya bayangkan sosok pria tua, galak, bawa palu sidang, dan hobi menceramahi soal moral. Ternyata salah besar.
Rizal muncul dengan kaos oblong dan celana pendek. Orangnya pendiam. Irit bicara. Beda jauh sama Helmi yang nyerocos terus kayak petasan banting. Tapi begitu Rizal bicara, pedasnya ngalahin Samyang level 5.
"Jadi ini jurnalis Indonesia tu? Yang katanya negaranya luas tapi macet di mana-mana?" sapa Rizal datar.
Mak jleb. Belum apa-apa ulu hati saya sudah kena tonjok verbal.
Akhirnya, saya terseret juga. Kami menginap dua malam di kawasan Bukit Bintang. Di sanalah saya menemukan sebuah kegilaan tata kota yang bikin iri setengah mati. Bukit Bintang itu ajaib.
Bayangkan Anda punya blender raksasa. Masukkan Plaza Indonesia (Jakarta), Braga (Bandung), Malioboro (Jogja), Pasar Semawis (Semarang), Simpang Tunjungan (Surabaya), dan Legian (Bali), ke dalamnya. Tekan tombol ON. Hasilnya? Bukit Bintang.
Semua ada di sana. Tumpplek blek. Tanpa jeda. Tanpa sekat.
Sore itu, Rizal mengajak saya ke Pavilion KL. Mewah. Dingin. Isinya tas-tas bermerek yang harganya bisa buat bayar cicilan KPR setahun. Orang-orangnya wangi, jalannya cepat, wajahnya glowing kena pantulan lampu etalase.
"Ini kalau di Jakarta, namanya Bundaran HI," kata saya sok tahu.
Rizal cuma mengangguk. "Tunggu lima menit lagi. Kita pindah alam".
Benar saja. Cuma jalan kaki lima menit. Catat! Lima menit, tidak pakai naik ojek, kami sampai di Jalan Alor. Dunia terbalik 180 derajat.

 1 month ago
40
1 month ago
40